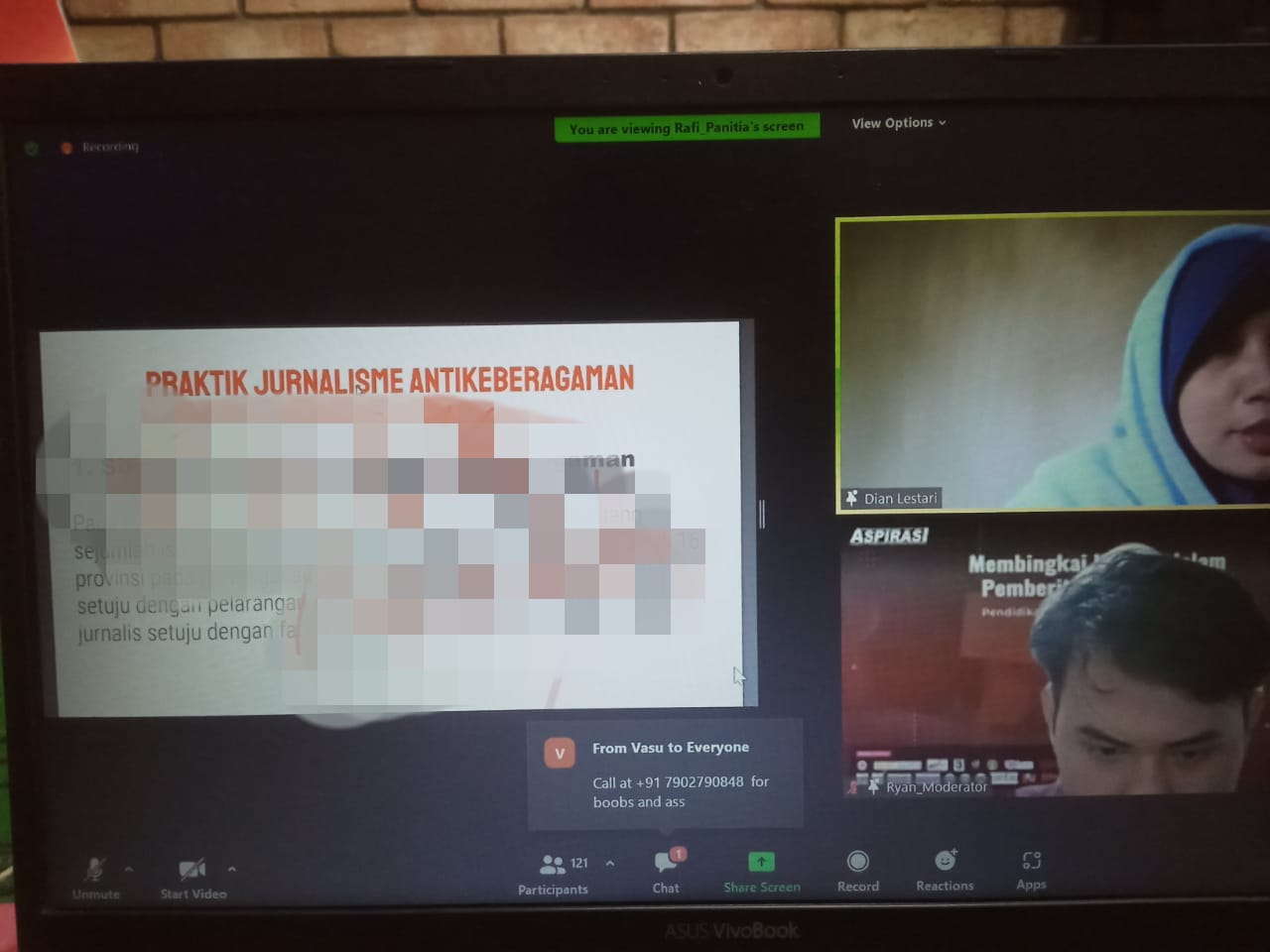Gigok Anurogo sedang berperan dalam pementasan Monolog 3 Generasi dengan judul “Sendika Kidung Panggung
Sumber Foto: Akrom/DinamikA
Oleh: Akrom, Asa, Ramadhon
Salatiga didekap hujan deras, menyisakan baju tebal dan obrolan hangatnya. Tak seperti biasanya Minggu malam, Senin (3/12), segerombol anak muda biasa berkumpul dalam ruang Monolog 3 Generasi, sebuah ruang pertemuan budaya kecil untuk mengakhiri pekan musim hujan. Rangkaian Mololog 3 Generasi berlabuh di kota ketiga yaitu Salatiga, tepat di Auditorium Kampus 1 Universitas Islam Negeri (UIN) Salatiga.
Bulan hangat nampaknya akan jarang kita temui, yang ada hanya aspal basah dan jalanan sepinya, tapi untuk beberapa orang memilih menyempurnakan minggunya dengan menonton monolog, hiburan orang biasa.
“Tiketnya 25 ribu mas,” ketus penjaga tiket.
Nominal 25 ribu rasanya mungkin tidak terlalu berat, jika kita tau bahwa uangnya untuk menghidupi lakon teater. Saya lalu menyapu pandangan sekeliling satu dua orang telah datang, sesegera mungkin memarkirkan sebisanya. Suasana berubah setelah memasuki lorong masuk menuju pangung utama, gelar monolog pertama berjudul “Anak Imitasi” oleh Iya Sekata suasana gelap, lampu sorot dan bau dupa menyengat menambah kesan magis namun hangat.
Panggung Menembus Generasi
Monolog 3 Generasi jadi panggung menembus ruang waktu, pertemuan tiga generasi 80-an, 90-an dan 2000-an menyajikan prespektif baru dalam menonton monolog.
Piwi selaku koordinasi acara monolog 3 generasi di Salatiga mengatakan, “monolog 3 generasi itu tidak terkonsep secara kontekstual, struktur keorganisasian siapa aja. Yang tertulis pasti itu hanya aktor, ada Mbah Gigok, Babe Sueb sama ada Mbak Iya. itu yang tertulis secara kontekstual dan itu sebagai inti dari acara monolog 3 generasi,” jelasnya.
“Itu anak saya……!!!” Teriak lakon menambah perasaan dalam.
Seorang gadis berlari antusias sambil memainkan boneka di tangannya. Rambut yang acak-acakan, raut wajah depresinya sangat tergambarkan. Kadang dia bisa membunuh dirinya sendiri lewat kata-kata atau malahan menyalahkan dirinya sendiri lalu berteriak, lakon yang tidak mudah diduga, yang bisa diduga dia depresi berat. Sejurus kemudian, gerakannya hyperactive bak kerasukan, ia yang semula lincah tak beraturan, kini gemulai bak perempuan dewasa.
Seiya Sekata atau yang kerap disapa Mbak Iya memerankan lakon monolog berjudul “Anak Imitasi”, wajah depresinya seketika berubah saat sesi diskusi, wajah sebenarnya periang dan murah senyum. Selain itu, dia juga membawa 2 anaknya yang masih balita. Pentas ini jadi kolaborasi angkatan tertua sampai termuda. Semangat dari para tokoh masih tetap utuh, walaupun sudah lanjut usia atau sudah menjadi ibu rumah tangga.
“Saya mendapat dukungan dari suami dan semangat adalah pendorong proses dari pentas ke pentas, proses ini bagi saya untuk menjaga kewarasan hidup,” ungkap Iya sambil cengengesan.

Zoex Zabidi atau sering dipanggil Babe Sueb melakonkan “Badut Terakhir” dalam pementasan Monolog 3 Generasi. (Sumber Foto: Akrom/DinamikA)
“Kalau bapaknya Jadi Gubernur, anaknya jadi Gubernur. Kalau bapaknya jadi Presiden, anaknya mau jadi…..,” sepenggal kata yang tak dilajutkan, lalu dilanjut gelak tawa penonton.
“lupakan, lupakan…. ini bisa jadi berbahaya,” lanjut badut berusaha mengampuni kata-kata sebelumnya.
Lakon Monolog kedua dengan babak “Badut Terakhir” jadi badut yang tak menyenangkan seperti biasanya, tapi tetap saja badut itu tetep bisa menghibur. Banyolan-banyolan yang sarkasme membaca keadaan zaman nampaknya jadi alternatif yang menghibur bagi penonton rakyat biasa, daripada pembacaan situasi politik yang selalu terbaca kaku dan serius. Zoex Zabidi atau sering di panggil Babe Sueb berhasil menpresentasikan itu.
Saat fase diskusi ternyata Babe Sueb juga tak mengkerdilkan itu, ia menyampaikan bahwa jadi seniman adalah pilihan, dan menjadi “Gembel” dan merdeka adalah pilihannya.
“Seniman akan lebih mulia dan lebih jujur ketika ia di luar sistem, seniman untuk mengkontrol system,” tampilan kumel khas teater pun berani mengatakan itu.
Setelah Temangung dan Semarang, Salatiga jadi pelabuhan ketiga Monolog 3 Generasi.
Iya juga menambahkan bahwa konsep ini ada sejak adanya covid namun baru terlaksana setelah lamanya covid menghilang.
“Acara Monolog 3 Generasi ini adalah menpresentasikan proses 3 orang dari generasi 80-an, 90-an dan 2000-an sebagai representasi masa dan gayanya masing-masing,” tambahnya.

Sebuah pertemuan penonton dan pelakon dalam sesi foto bersama setelah diskusi Monolog 3 Generasi. (Sumber Foto: Panitia Getar)
Sendika Kidung Panggung
Menuju babak pungkas, seorang kakek berjalan bungkuk sakit pinggang, tangan kanannya membawa payung mesti tak hujan sedangkan kanan kirinya membawa sebotol. Mata penonton seolah menghakimi pria paruh baya itu, memelas karena mengakhiri usia senja dengan kelakuan sedemikian rupa.
“Gakpapa…apa dikira Ciu itu rasanya keras saja, Ciu itu rasanya juga bermacam-macam lo!”
“La wong, Republik rasa kerajaan aja kok,” seketika panggung ini riuh, kakek-kakek ini ternyata tidak begitu menyebalkan seperti orang mabuk pada umumnya.
Gigok Anurogo atau sering dipanggil Mbah Gigok, bagi pecinta teater namanya terkenal di seantero Solo Raya. Hidup dia memang dedikasikan untuk teater, hampir separuh abad atau lebih tepatnya 47 tahun berteater sejak 1974. Pria yang lahir pada tanggal 23 Mei 1955, baginya teater bukanlah sekadar berkegiatan seni semata melainkan salah satu bagian dari ibadahnya dalam wujud seni teater.
“Hidup saya untuk teater, anak saya juga di teater. Wah saya juga mau bikin dinasti teater,” kata Mbah Gigok sambil tertawa saat diwawancarai di belakang panggung.
Sendiko Kidung Panggung semula adalah naskah tugas akhir milik anaknya. Pada mulanya naskah teater yang ditulis dan dikarang serta sekaligus disutradarai anak Mbah Gigok. Pada usia ke 68-nya lakon masih luwes menceritakan tentang bagaimana rekan-rekan lakon ketoprak yang sudah mulai hengkang dan sepi penonton.
“Cerita ini tentang kegelisahan seorang seniman terhadap nasib kesenian tradisi. Bagaimana kesengsaraannya, bagaimana kesenian tradisi sekarang ini terpingirkan, bisa panen pun setiap tahun kampanye tapi sekarang kan sudah tidak lalu lagi,” ungkapnya.
Gigok juga menjelaskan tentang teknik dalam seni pertunjukan, tentang teori bisnis akting yang memang gimik-gimik itu dilontarkan sesuai kondisi sosial masyarakat sekarang ini. Bagi dia wajah politik sekarang tak begitu memperdulikan soal budaya.
“Dari semua debat presiden tidak ada satupun yang membahas soal budaya, kalau memang mereka masih menganggap budaya penting untuk peradaban, mengapa?” walaupun sudah malam raut wajah Gigok di usia senja masih terlihat jelas segar.
Ia juga sempat menyinggung bahwa masyarakat pun juga punya hak agar tau bahwa ada salah satu calon presiden yang memiliki dosa terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia. HAM menjadi persoalan penting karena Gigok kecil mempunyai trauma masa lalu keluarganya pasca tragedi 65, di mana masa mudanya di hatui cap Tapol yang disematkan pemerintah saat itu kepada orang tuanya.
“Terima uangnya, jangan coblos orangnya, ini salah satu pembodohan yang sangat luar biasa,” ucapnya dengan nada naik.
Bagi dia politik saat pesta pemilu sering bertentangan dengan budayawan, politik semacam itu baginya mengajarkan masyarakat melihat uangnya, bukan melihat kualitas calon presiden melalui visi misinya.
Hawa dingin Salatiga seketika berubah jadi hangat, sudah tak tau rokok kretek keberapa yang dihisap, dan kopi tinggal seperempat pula. Gigok menjelaskan bahwa posisi seniman dan budayawan harus jelas.
“Apapun Rendra-Rendra keseniannya, tanpa berbicara penderitaan lingkungan, omong kosong!,” tutup dia dengan pasti.