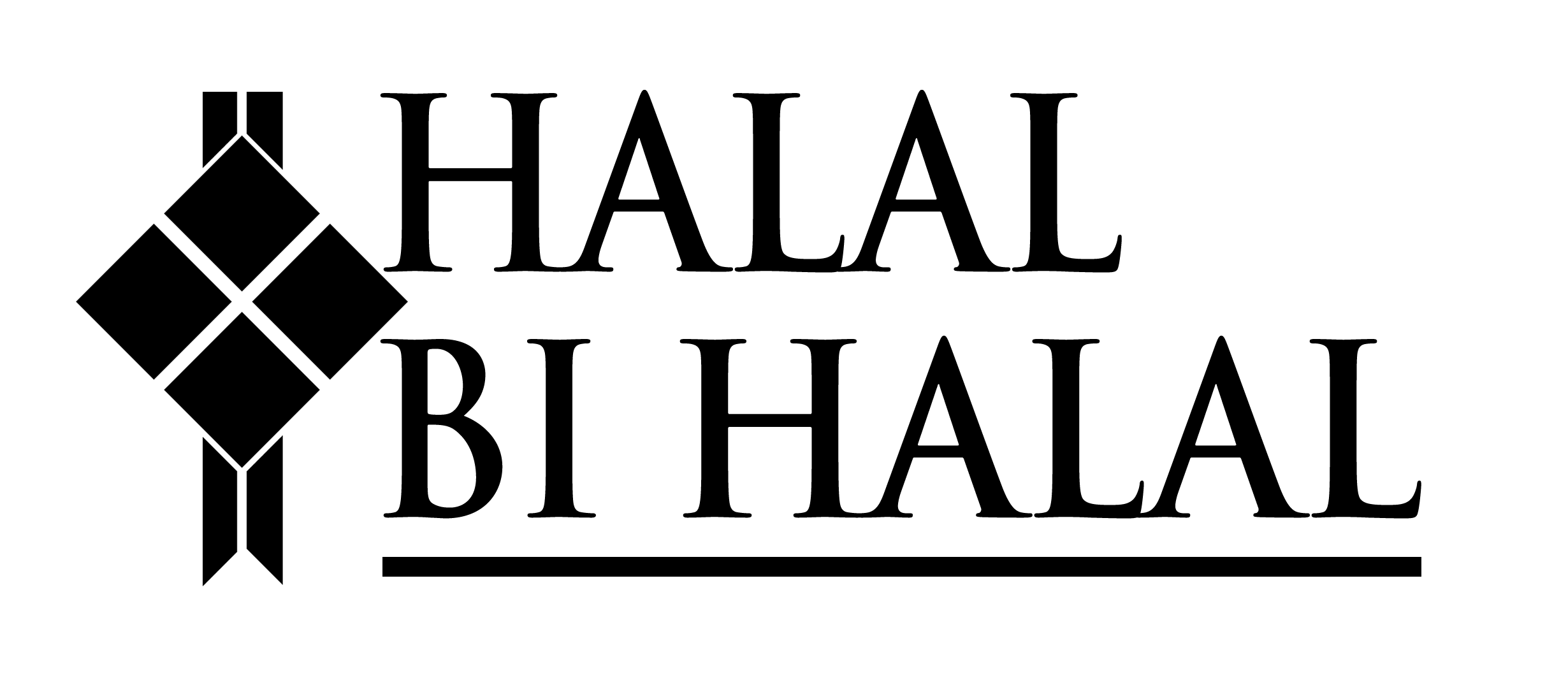Sumber Foto: Freepik
Oleh: Ahmad Ramzy
Sebuah perandaian yang mungkin sebagian orang akan menganggap ini sebagai lelucon, namun sebagian orang lainnya akan menilai saya memiliki cita-cita mulia, yang mengedepankan kontribusi utama dari seorang pendidik terhadap bangsa.
Kaum intelektual universitas kali ini menjadi pekerjaan yang cukup banyak digandrungi oleh orang-orang yang memiliki ketertarikan untuk mencerdaskan masyarakat melalui mahasiswa, terutama apabila kita mengutip pada alinea keempat Pembukaan UUD 1945, termaktub dengan jelas bahwa Pemerintah Negara Republik Indonesia melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Hal tersebut menjadi landasan para intelektual yang berjuang di medan perlawanan tehadap kebodohan dan penindasan.
Tidak dapat dipungkiri, bahwa tugas intelektual sangatlah fundamental untuk kemajuan suatu bangsa. Seperti apa yang terjadi selepas bom di kota Nagasaki dan Hiroshima yang meluluhlantakkan Negeri Matahari Terbit —Jepang pada 6 dan 9 Agustus 1945, konon katanya Kaisar Jepang mempertanyakan nasib guru atau tenaga pendidik yang masih selamat di kedua wilayah tersebut.
Tugas seorang intelektual, dianggap mampu mengubah suatu perjalanan bangsa, dari fase dekaden menuju fase kemajuan. Tanpa adanya seorang intelektual, mungkin sebuah bangsa akan selamanya berada di fase dekaden dan kebodohan saja. Seorang intelek dengan pengetahuannya, akan mampu mensiasati zaman yang mengalami keterbelakangan. Gramsci pun percaya, bahwa pengetahuan itu bukan hanya doktrin, tapi kesegaran gagasan pengubah jalannya sejarah.
Perubahan suatu sejarah, dapat dilihat secara seksama dengan apa yang terjadi pada fenomena revolusi maupun reformasi. Ketika dikontekskan di Indonesia, di era Orde Baru, tepatnya di tahun 1998, terlihat dengan jelas bagaimana perubahan itu dapat terlaksana oleh “syahwat” perubahan yang diimpikan oleh kaum intelektual. Bagi seorang intelektual, perlawanan dan perubahan bukan suatu hal yang tidak mungkin terjadi.
Di masa tersebut, ruang-ruang kelas bukan satu-satunya ruang untuk belajar dan berdiskusi. Namun, di manapun tempat yang mereka tempati atau singgahi, adalah ruang berdialektika bagi mereka. Mereka yang didapuk sebagai kaum intelektual, menolak keras untuk berada di menara gading. Tidak heran, di masa itu banyak intelektual universitas turun ke jalan untuk menentukan nasib bangsanya secara langsung.
Penjelasan singkat di atas, bukan melegalkan tindakan romantisasi, karena saya pribadi muak dengan tindakan tersebut. Tentunya, kita bukan orang kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya dari para tokoh-tokoh penggerak yang mengubah jalannya sejarah, karena kita adalah diri kita sendiri, yang memiliki andil untuk menaruh kepedulian terhadap mereka yang terkungkung oleh ketidakadilan dan kebodohan, dengan cara yang sama atau berbeda menyesuaikan zamannya.
Biarlah ampas yang tersisa kita bersihkan saja, bukan digunakan kembali atau dipindahkan ke gelas lainnya, karena kita seharusnya tidak membutuhkannya lagi. Bukan secara personal yang perlu kita teruskan, tapi gerakannya-lah yang perlu kita lanjutkan dan kembangkan sesuai dengan zamannya.
Dengan semangat perubahan yang dicita-citakan, mengajar adalah momentum yang akan memudahkan proses yang dicanangkan. Tak heran, intelektual universitas, dalam hal ini dimaksudkan ialah dosen, mengambil peran penting memajukan bangsa dan mengontrol rezim yang otoriter.
Dosen: Penggugah Gairah Gerakan Mahasiswa
Ibarat mobil yang membutuhkan bahan bakar, maka mobil itu harus diisi bahan bakarnya terlebih dahulu agar mampu berjalan. Anggap saja mobil adalah mahasiswa dan dosen adalah bahan bakarnya. Tanpa seorang dosen, apalah jadinya seorang mahasiswa itu? Diam di kelas, bersenda gurau yang tidak penting, menguap karena kantuk, dan hal-hal lainnya yang hanya bersifat mudharat.
Tersempatlah saya bertemu dengan Eko Prasetyo, dirinya selalu mengenang masa-masanya berkuliah dengan Artidjo Alkostar, dimana dirinya merasa pernah dicuci otaknya oleh dosennya itu saat masih berkuliah di UII sekitar tahun 90an. Dalam ceritanya ia selalu berkata, “yang di kelas ini kemarin ikut berdemonstrasi tunjuk tangan!”, “kamu ikut? Baik, nilaimu saya berikan A, silakan keluar dari kelas saya.”
Cerita tersebut seakan tidak lekang oleh zaman, bagi kita yang mendengarkannya pun merinding dengan keberanian dosen yang memupuk semangat mahasiswanya untuk tampil sebagai pengubah nasib sebuah bangsa, tentu hal ini yang sudah jarang sekali kita dapatkan dari dosen-dosen yang mengajar kita. Bahkan, tidak sedikit yang beranggapan bahwa dosen hari ini, lebih mementingkan kualitas pribadi dan kampus tempatnya mengabdi dan mengajar. Sehingga, kampus menjadi objek yang dikultuskan dan siapa pun menjadi tidak berani untuk mengkritik kesalahan-kesalahan yang dilakukan.
Lebih buruknya lagi, adapula dosen yang mangkir dari jadwalnya mengajar dengan alasan-alasan yang tidak masuk akal. Kadang kala tindakan ini disenangi oleh mahasiswa karena kelasnya menjadi free class, namun bagi saya tindakan ini adalah bentuk dosa besar dan pelanggaran yang dilakukan seorang dosen, tentu lebih baik dosen tersebut tidak usah mengajar lagi, karena sikapnya telah mencederai nilai moral yang tersematkan di diri seorang intelektual.
Melihat hal itu, seandainya saya seorang dosen, saya akan menjalani proses belajar mengajar seperti dosen yang pertama, bukan hanya mendorong mereka untuk melakukan tindakan demonstrasi, namun juga berusaha untuk memupuk kesadaran mahasiswanya melalui ruang kelas, agar senantiasa berani menegakkan keadilan yang disisihkan oleh mereka yang berkuasa.
Mahasiswa perlu diasah untuk menjadi tajam, menusuk bentuk-bentuk ketidakadilan yang mengerubungi mereka dan sebangsanya, bukan menjadi majal dan memilih diam ketika adil menjadi barang yang tidak gratis lagi untuk mereka dan sebangsanya nikmati.
Kemudian, dosen-dosen yang mengajar seharusnya tidak perlu merasa khawatir dengan bidang keilmuan yang dimiliki sesuai dengan kondisi masyarakat atau tidak. Mereka memiliki tugas mencerdaskan dan membentuk mahasiswanya untuk peduli dengan segala apapun yang ada di sekitarnya, melalui bidang keilmuannya masing-masing.
Contohnya saja akan saya jabarkan di sini. Pertama, dosen di bidang hukum dapat menjelaskan betapa biadabnya pemerintah masa kini yang mengesampingkan hak asasi manusia warganya, bahkan warga tidak diberikan banyak ruang untuk menentukan nasibnya sendiri. Kedua, dosen di bidang sosial dapat menjelaskan gejala-gejala yang terjadi pada masyarakat, bagaimana membangun kohesi sosial dan melancarkan instrumen pergerakan, menganalisa kemiskinan akibat adanya ketimpangan kelas, dan lain-lain. Lalu, adapun dosen di bidang ekonomi misalnya, dosen ini dapat memberikan penjelasan terkait dengan ketimpangan ekonomi, membangun ekonomi yang bersifat merakyat dan lain-lain.
Tiga contoh dosen yang memiliki bidangnya masing-masing, adalah salah satu cara untuk dapat membangun paradigma keadilan di benak mahasiswa-mahasiswanya. Pun melalui bidang keahlian lainnya memiliki peran yang sama juga tentunya. Ketika seorang dosen mampu menjalankannya dengan baik, bukan tidak mungkin gerakan mahasiswa nantinya akan benar-benar berjalan dan kemampuan memahami nasib rakyat terlaksana dengan baik.
Satu hal yang perlu diketahui bersama, bahwa tugas seorang pendidik bukan hanya sebatas mengisi kuliah dengan retorika laiknya seorang pendakwah di muka umum, yang menjelaskan panjang lebar tanpa adanya himbauan kepada mahasiswanya untuk melakukan praksis dari gagasan-gagasan yang disampaikan. Untuk itulah, dosen yang baik adalah dosen yang berjuang mengasah kepekaan, kepedulian yang terpenjara di alam bawah sadar mahasiswanya tersebut.
Seperti yang ditekankan oleh Paulo Freire dalam Pendidikan Kaum Tertindas, bahwasanya tugas seorang pendidik harus mampu menghantarkan rasa kepedulian muridnya dengan memposisikan diri mereka untuk melihat realita yang dihadapi oleh masyarakat. Namun, proses praksis yang dihadapkan mahasiswanya tersebut tidaklah mengubah esensi seorang intelektual untuk mampu melibatkan masyarakat sebagai subjek perubahan, karena sejatinya masyarakat bukanlah objek untuk kepentingan ilmiah semata. (Freire, 2019)
Dilematis Kehidupan Intelektual
Sekilas ingin saya sampaikan di sini beberapa peristiwa-peristiwa yang terjadi dari keberanian seorang dosen, ketika dirinya merasa geram dengan ketidakadilan yang didapati oleh masyarakat.
Siapa yang tidak mengenal Arief Budiman? Sang intelektual sekaligus dosen yang pernah mengajar di Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW), Salatiga, ini pernah melakukan tindakan-tindakan yang lihai dan sangat menantang. Mulai dari Pemilu 1973, Arief dan kawan-kawannya mencetuskan gerakan Golput, sebagai bentuk ketidakpercayaan terhadap rezim Soeharto yang diktator dengan kendaraan politiknya, yaitu Golkar. Dominasi rezim Soeharto cenderung hanya menyajikan prinsip-prinsip tiranis dan amoral.
Tidak hanya itu, Arief dan kawan-kawan dosen UKSW lainnya juga pernah melakukan mogok mengajar atas penolakan terhadap pemilihan rektor yang tidak adil. Usut punya usut, rektor yang terpilih tersebut memiliki hubungan yang “mesra” dengan presiden Soeharto. Akhirnya, keberaniannya itu berujung pada pemecatan Arief dan dosen lainnya di tahun 1995.
Peristiwa yang dilakukan oleh Arief Budiman dan lainnya, sudah jarang terlihat di ruang-ruang kelas kampus. Terakhir, saya melihat peristiwa yang hampir serupa, ketika seorang Kepala Prodi (Kaprodi) Magister Sosiologi Agama UKSW, yakni Rama Tulus Pilakoannu, diberhentikan dari jabatannya, karena melakukan tindakan penegakkan keadilan atas nasib mahasiswa UKSW yang cepat atau lambat akan terusir dari tempat tinggalnya di asrama, dengan dalih pembangunan dan renovasi asrama. Kini beliau memilih untuk mengundurkan diri dari mengajar akibat sikap totaliter dari pimpinan UKSW tempatnya mengajar.
Secara pribadi, peristiwa ini merupakan peristiwa yang tidak sering terjadi, bahkan terkesan mahal sekali bilamana ditukar dengan uang. Lalu, jika melihat dosen-dosen di masa sekarang ini, tidak jarang mereka terjebak pada kotak-kotak yang selalu membatasi dengan berbagai alasan, mulai dari perbedaan latar belakang, ormas/organisasi sejenisnya, etnis, agama, dan lainnya. Tidak heran, kita akan berjumpa dengan persaingan dosen-dosen tersebut, mencari muka dan opportunis demi perihal akademis maupun jabatan.
Saling sikut-menyikut, melanggenggkan sikap dogmatis dan apologetis menjadi aktivitas sehari-hari yang dilancarkan untuk menentukan kepentingan jabatan yang mengikat diri mereka sebagai seorang dosen. Bahkan, sikap itulah yang akhirnya ditiru dengan baik oleh mahasiswanya, sehingga dapat terlihat dengan jelas bagaimana tensi yang mengikat daripadanya. Rasa kebersatuan sulit untuk terjadi, ketika sikap ini terus menjadi makanan sehari-hari. Hingga akhirnya, berujung pada ketidakmampuan kaum intelektual kampus untuk menguatkan basis gerakan secara massif dan solid.
Padahal dengan jelas Gramsci memberikan penekanan tugas seorang intelektual, terutama sebagai intelektual organik, bahwa seharusnya seorang intelektual tidak hanya dinilai dari kefasihannya berbicara, namun meliputi partisipasi aktif dalam kehidupan praksis, sebagai pembangun, organisator, penasihat tetap dan memiliki semangat juang abstrak yang tinggi (Amsalis, 2022). Sayangnya intelektual hari ini, sering terjebak di dalam kotak-kotak yang terbentuk, bahkan sengaja dibentuk di sekeliling mereka, pun mereka abai dengan kondisi di sekitarnya.
Sebagai seorang intelektual, tugas sejatinya ialah memberikan lampu bagi mereka yang berada di jalan kegelapan, melegakan dahaga mereka yang kehausan, membangun jembatan di antara dua tebing yang berjarak untuk memberikan akses jalan. Tugas-tugas ini mulai terasingkan, para dosen lebih mengutamakan nilai akademis di ruangan, menghalalkan tindakan plagiasi, bertindak melecehkan mahasiswanya sendiri, sering mangkir dari jadwal belajar mengajar, lupa akan tanggung jawab mengasah moral mahasiswa terhadap realita di masyarakat, mengejar jabatan tinggi semata, dan tindakan lainnya.
Apabila tugas seorang intelektual seperti halnya yang dilakukan oleh Arief Budiman dkk atau Rama Tulus sendiri, secara otomatis, mereka akan didepak dari kampusnya. Ditambah lagi bilamana seorang dosen tersebut tidak memiliki pekerjaan sampingan, nasib anak dan istrinya patut dipertanyakan.
Urusan perut adalah segalanya, ketika rasa takut ini selalu membayang-bayangi di benak seorang dosen, maka pupuslah harapan kita untuk melawan ketidakadilan. Tidak jarang ancaman ini senantiasa mengintai dosen manapun. Kebanyakan kampus memang lebih menginginkan pemujaan daripada kritikan, akhirnya kampus telah menjadi objek pengkultusan—yang “suci”.
Persatuan Dosen Adalah Jawaban
Perlukah kita terus bercokol memikirkan nasib setelah kita didepak dari kampus yang mementingkan pemujaan, yang menjerumuskan kita ke dalam jurang kemandekan? Tentunya tidak. Ancaman itu seharusnya dapat disiasati dengan strategi yang konkrit.
17 Agustus 2023 di Salemba, Jakarta, telah terjadi saksi sejarah dengan terbentuknya Serikat Pekerja Kampus (SPK). Momen tersebut bertepatan dengan momen kemerdekaan, terbentuknya SPK adalah simbol kemerdekaan bagi para tenaga pendidik kampus. Serikat ini merupakan salah satu bentuk strategi menghadapi ancaman terhadap para dosen.
Berdasarkan tujuannya, SPK didirikan untuk mengkritisi “penyakit” di kampus. Mulai dari obral honoris causa, jabatan professor, eksploitasi mahasiswa, plagiasi karya ilmiah, investasi kampus yang mengutamakan profit oriented, dan segala permasalahan yang membuat universitas tidak berjalan dengan baik.
Meskipun SPK bukan suatu yang baru, karena di beberapa universitas lainnya juga sudah membuat serikat dosen yang sama untuk melawan bentuk-bentuk yang dibangun oleh universitas yang melanggengkan kekuasaan. Alasannya sama, untuk menghimpun kekuatan para dosen.
Perjuangan di jalur individu memang akan membawa pada ketidakberuntungan, atau dalam hal ini mudah untuk dipatahkan. Ketika semangat persatuan ini terbentuk, yang didasari atas perasaan yang sama, maka mungkin saja terdapat jalan terang yang dapat diperoleh oleh para pengajar tersebut.
Proses advokasi dari dosen yang didepak akan lebih mudah, karena kesatuan dan kepedulian itu telah terbentuk. Apabila serikat pengajar ini tidak ada, mudahlah sekali dosen-dosen ini hilang begitu saja dari rekaman sejarah, mereka didepak dan dilupakan. Dengan adanya serikat inilah, rasa kebersamaan dan tolong-menolong sesama pengajar akan terlihat.
Demi memegang prinsip yang terdapat di UU No. 12 tahun 2012, terutama pada pasal 6 ayat b, bahwa Pendidikan Tinggi harus berupaya untuk bersikap demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai agama, nilai budaya, kemajemukan, persatuan, dan kesatuan bangsa. Kini teramat disayangkan, universitas kampus cenderung abai dengan poin tersebut, sehingga banyak dosen yang akhirnya didepak dengan alasan melakukan tindakan yang menghasut dan mencederai norma-norma kode etik seorang pengajar.
Tentu ini adalah lelucon, universitas merasa dirinya tidak memiliki kesalahan, padahal kesalahan itu seringkali berjatuhan di sepanjang jalan yang dilalui. Bagaikan melempar batu ke samudra, dari luarnya kita tidak akan tau bagaimana, namun di dalam samudra itulah yang akan mengetahui seberapa jauh batu itu menusuk ke dasar terbawah. Itulah barangkali yang terjadi di dalam kampus, tak ayal di dalamnya akan merasakan bagaimana petinggi kampus bersifat represi terhadap kritikan.
Semangat kolektif yang dibangun melalui serikat ini merupakan bentuk yang dibicarakan oleh Pierre Bourdieu (Mutahir, 2011) di dalam karyanya, semangat inilah yang nantinya bukan hanya membangun kesadaran bertindak peduli dengan sesamanya, namun mencakup juga kepedulian atas nasib yang diderita oleh masyarakat dengan maraknya ketidakadilan.
Daftar Pustaka
Amsalis, Y. (2022). Antonio Gramsci Sang Neo Marxis. Yogyakarta: BASABASI.
Freire, P. (2019). Pendidikan Kaum Tertindas. Yogyakarta: Penerbit Narasi.
Mutahir, A. (2011). Intelektual Kolektif Pierre Bourdieu. Yogyakarta: Kreasi Wacana.