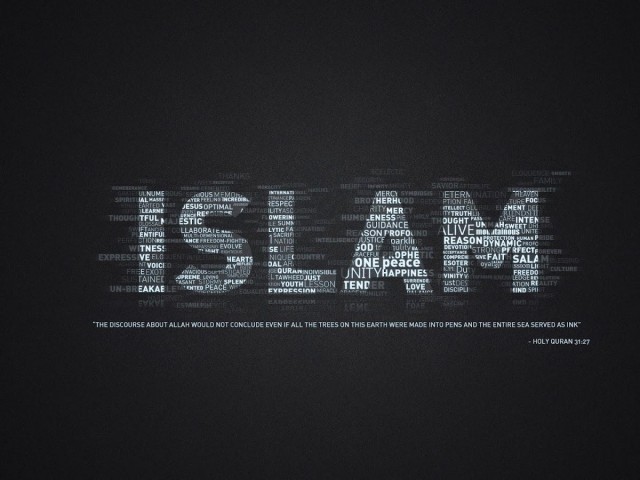Sumber Foto: geger.id
Oleh: Thoriq Baihaqi Firdaus
Pendidikan di banyak negara, khususnya negara maju menjadi prioritas utama, karena pendidikan menjadi jembatan visi negara dan cetak biru pembangunan dan cita-cita berbangsa dan bernegara.
Pendidikan dipercaya sebagai suatu usaha mengubah nasib bangsa. Contoh saja Jepang, pasca bom atom meledak di Hiroshima dan Nagasaki, mula-mula yang dibangun adalah bidang pendidikan. Padahal dunia menilai akibat hal ini Jepang akan menjadi negara terbelakang dan terpuruk. Nyatanya, hingga hari ini Jepang menjadi salah satu negara dengan perusahaan otomotif terbesar di dunia dan memiliki kelebihan-kelebihan lainnya. Hal ini menunjukkan peran pendidikan terhadap kontribusi suatu negara di masa mendatang.
Negara, selaku pemangku hajat memiliki tanggung jawab memberikan kesempatan setiap warga negaranya untuk secara bebas mengenyam pendidikan. Hal ini termaktub dalam UUD 1945 amandemen keempat pasal 31 ayat 1 yang secara gamblang memuat hak warga negara memperoleh pendidikan. Namun pasal tersebut hanya menjadi “macan kertas”, karena implementasi di kehidupan sehari-hari berkata lain.
WTO dan IMF menjadikan pendidikan sebagai komoditas yang dapat diperjualbelikan. Pendidikan yang seharusnya memiliki derajat dan semestinya diperlakukan lebih tinggi dibanding sektor-sektor lainnya akhirnya tidak lepas juga dari jerat aturan liberalisasi yang digembar-gemborkan. WTO memasukkan bidang pendidikan ke dalam bidang tersier.
Argumentasinya bahwa pendidikan termasuk ke dalam kategori industri yang mengubah benda fisik (physical services), keadaan manusia (human service) dan benda simbolik (information and communication services), di mana kegiatan pokoknya adalah mentransformasi orang yang tidak berpengetahuan dan tidak memiliki keterampilan menjadi memiliki pengetahuan dan keterampilan. Prinsip dan peraturan dari WTO adalah adanya jaminan atas perdagangan bebas.
Sehingga semua bentuk kebijakan dan tindakan yang menghalangi atau mengurangi persaingan bebas harus dihilangkan. WTO membagi dua kategori liberalisasi perdagangan dunia, yaitu GATT/General Agreement on Tariff and Trade (Kesepakatan Umum Tentang Tarif dan Perdagangan) dan GATS/General Agreement on Trade in Services (Kesepakatan Umum Peradagangan Sektor Jasa). Melalui yang disebut terakhir inilah, salah satu bidang usaha yaitu pendidikan ditetapkan masuk di dalamnya, dapat diperjualbelikan dalam pasar global.
Indonesia termasuk salah satu negara yang menandatangani pembentukan WTO dan GATS, konsekuensinya Indonesia harus tunduk pada ketentuan-ketentuan WTO/GATS ini dalam meliberalisasi, salah satunya sektor pendidikan. Ratifikasi WTO ditandai dengan disahkannya Undang-undang No. 7 tahun 1994 tentang pengesahan Agreement Established The World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia).
Selang 11 tahun kemudian ditandatangani penandatangan lanjutan GATS di tahun 2005. Setelah peritiwa itu, pemerintah kemudian mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) No. 76 tahun 2007 dan Perpres tahun 77 tahun 2007 yang menyatakan bahwa pendidikan termasuk sektor yang terbuka bagi penanaman modal asing, maksimal sampai 49 persen.
Dengan nalar seperti ini, maka jelas bahwa subyek peserta didik sebagai modal manusia (human capital), dan kemudian upaya negara dalam bertanggung jawab terhadap warga negara akan kebutuhan pendidikan terus digerus, diperkecil bahkan dihilangkan. Sedangkan peranan korporasi melalui modal asing diupayakan dominan. Kenyataan ini tak ubahnya merupakan korporatisasi pendidikan, atau swastanisasi institusi-institusi pendidikan.
Hal ini menyebabkan pergeseran paradigma pendidikan menjadi ke arah komersialisasi yang kapitalistik. Pendidikan dan ilmu pengetahuan dianggap sebagai komoditas yang bebas diperjualbelikan. Inilah logika komersialisme pendidikan yang lebih berat pada logika ekonomi kapitalis, bukan lagi berparadigma intelektual, kebudayaan dan humanisme.
Lomba Mengejar Keuntungan
Peraturan perundang-undangan membagi pengelolaan keuangan di PTN menjadi Satker, BLU dan PTN-BH. Perguruan tinggi berbondong-bondong mengejar status tertinggi, yakni PTN-BH, karena pengelolaan keuangan yang mandiri serta lebih efisien dalam pengelolaannya. Terbaru ada 21 kampus yang berstatus PTN-BH. Pada perlombaan mengejar PTN-BH, UIN Salatiga berada pada posisi BLU.
Bila Satker setiap pendapatannya harus disetorkan ke kas negara, maka BLU hanya melaporkan pendapatan non pajak yang dikelola secara otonom ke negara. Berbeda lagi dengan PTN-BH, seluruh pendapatan dikelola secara otonomi penuh untuk kemajuan perguruan tinggi.
Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang BLU menyatakan bahwa BLU dapat memungut biaya dari masyarakat sebagai imbalan atas barang/jasa layanan yang diberikan. Sedangkan, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang BLU menyatakan bahwa BLU tidak mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
Aturan-aturan ini bila dilihat secara seksama menjadi suatu paradoks tanpa titik terang yang konkrit.
Melihat keadaan senyatanya di UIN Salatiga sekarang ini, komersialisasi pendidikan sudah menggerogoti lingkungan kampus. Permasalahan tentang transparani UKT, jas almamater yang belum selesai, simpang siur tentang BLU, penyewaan toga, toffle berbayar, dan seabrek permasalahan lainnya. Mahasiswa terdampak secara langsung, akan tetapi sedikit mahasiswa yang sadar dan paham akan hal tersebut.
Gambaran sederhanannya, banyak mahasiswa yang kuliah sambil bekerja, hal tersebut selain sebagai sampingan pendapatan ataupun digunakan untuk mengisi waktu luang, yang pasti uang hasil kerja mereka digunakkan untuk membayar UKT dan kebutuhan lainnya seperti KKL, PPL, dan KKN. Hal yang paling terlihat dan terasa bagi mahasiswa mengenai komersialisasi pendidikan adalah masih adanya penarikan uang di luar UKT dengan dalih pembayaran kegiatan mahasiswa seperti KKL, PPL, dan KKN.
Sedangkan dalam Keputusan Menteri RI Tahun 2022, Kemenag melalui Yaqut Cholil Qoumas mengeluarkan keputusan yang berbunyi ‘Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri dilarang memungut uang pangkal dan pungutan lain selain UKT PTKIN dari mahasiswa baru program diploma dan program sarjana’. Aturan dan realitas sudah tidak sejalan, sedangkan fungsi kontrol atas aturan abai dalam menyikapi, pada akhirnya mahasiswa yang menjadi korban dari kesewenang-wenangan institusi.
Setelah IAIN bertransformasi menjadi UIN, pola pengelolaan keungan ikut berubah, yang dulunya Satuan Kerja (Satker) sekarang menjadi BLU, hal ini sudah menjadi perdebatan sengit di ranah atasan, sedangkan mahasiswa masih enggan untuk tau dan impotan.
Maka dari situ, dibutuhkan elaborasi mendalam tentang BLU khususnya dan komersialisasi pendidikan pada umumnya. Tulisan ini mencoba menjembatani mahasiswa untuk dapat memahami dan sadar tentang polemik komersialisasi pendidikan yang terbingkai dalam semangat kapitalistik.