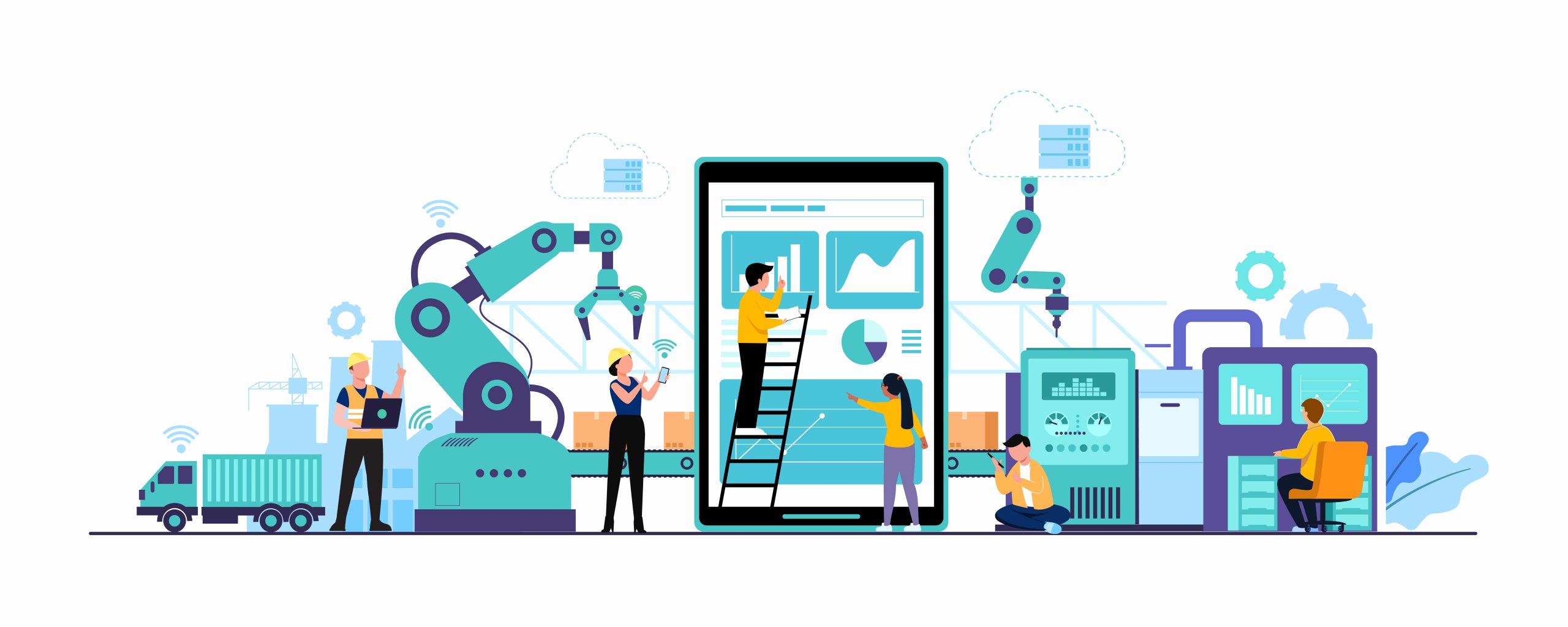Sumber Foto: Pinterest
Oleh: M Ghithrof Danil Barr
Kemerdekaan adalah nasi, dimakan jadi tai.
Terdengar jorok memang penggalan puisi diatas. Penulis yakin di balik pilihan kata yang di luar sopan santun itu, ada rasa kecewa yang sangat mendalam dari diri Wiji Thukul. Kemerdekaan hanyalah omong kosong baginya. Sama seperti yang dirasakan oleh bapak republik kita, Tan Malaka. 24 Januari 1946, dihadapan Sukarno-Hatta dan Agus Salim, Ia mengeluarkan segala kekecewaannya kepada para pendiri negara. Negara yang belum mencapai umur setahun itu belum benar-benar merdeka. Ia merasa bahwa kemerdekaan hanya dirancang untuk para elitis, yang mendadak sumringah menjadi borjuis, suka ria menjadi ambtenaar; kemerdekaan hanya milik segelintir orang, bukan milik rakyat.
Tan Malaka menganggap bahwa rakyat Indonesia belum sepenuhnya merdeka. Kemerdekaan haruslah seratus persen. Di bulan lahirnya negeri ini, di tengah hiruk pikuk perayaan, perlombaan agustusan memperingati kemerdekaan negara tercinta yang ke 80. Penulis ingin mengajak pembaca sedikit menyelami samudera pemikiran Ibrahim Datuk Tan Malaka mengenai kemerdekaan seratus persen, atau kalau istilah dalam sejarah kemerdekaan India; Purna Swaraj. Kemerdekaan penuh.
Pandangan Tan Malaka Tentang Kemerdekaan
Kemerdekaan rakyat Indonesia saat itu menurut Tan Malaka ibarat burung Gelatik. Ia bebas gembira berterbangan. Namun, ia selalu berada dalam ancaman diintai oleh musuhnya, elang bahkan diburu oleh manusia. Rakyat rentan ditindas oleh mereka yang berkuasa. Kemerdekaan bisa terlindungi oleh dua faktor. Pertama, raja atau pemimpin yang adil. Kedua, undang-undang atau konstitusi yang berpihak pada rakyat. Dua hal tersebut dapat membatasi dari oknum penguasa yang merenggut kemerdekaan rakyatnya.
Musuh utama bagi kemerdekaan adalah para kapitalis, para kaum fulus. Merekalah yang mendanai, dan bebas menentukan siapa yang akan menjadi wakil rakyat dengan uang yang mereka miiki. Wakil rakyat yang dipilih tentu yang menguntungkan dan berpihak pada kepentingan mereka. Sebesar apapun suara rakyat akan kalah dengan kekuatan mereka. Sehingga, seringkali kebijakan pemerintah tidak berpihak pada rakyat.
Tan Malaka juga mengkritik kebijakan pemerintah yang terkesan lembek terhadap penjajah. Ia menolak diplomasi atau perundingan. Pemerintah cenderung melakukan usaha diplomatik ketimbang melakukan perlawanan secara radikal. Di masa pemerintahan kabinet Sjahrir, terjadi beberapa perundingan dengan kolonialisme Belanda yang sangat merugikan Indonesia, bahkan wilayah Indonesia saat itu tinggal Jawa Tengah, Sumatra dan Yogyakarta. Menurutnya, diplomasi sama saja seperti kaki tangan imperialis. “Kalau ada maling masuk ke rumahmu, usir dia. Kalau perlu pukul. Jangan ajak dia berunding”.
Kemerdekaan bukan tanpa batas. Bagi Tan Malaka, kita yang memiliki kemerdekaan tidak boleh merebut kemerdekaan milik orang lain, milik bangsa lain. Maka dari itu, kolonialisme sangatlah bertentangan dengan konsep kemerdekaan. Seperti halnya kolonialisme yang tidak memberi ruang bagi masyarakat pribumi, pemerintah yang zalim juga tidak memberi ruang bagi rakyatnya sendiri. Suara rakyat dibungkam, hak-hak mereka direbut. Didengar ketika kampanye. Suara rakyat hanyalah angka, dalam merebutkan kursi semata.
Dalam buku Madilog-nya, Tan Malaka menegaskan bahwa lemahnya pendidikan dan pengetahuan bisa menjadi sebab langgengnya penindasan. Kita bisa melihat masih banyak masyarakat kita yang belum mendapat akses pendidikan. Problem pendidikan adalah inti dari kondisi keterjajahan. Mitos misalnya, seringkali digunakan untuk menjajah, membunuh independensi manusia. Rakyat yang tidak menggunakan nalar rasionalnya akan senantiasa diperbudak oleh rezim yang berkuasa.
Kita-lah Ratu Adil!
Ya, agak berat mungkin ketika kita berbicara mengenai pemikiran sang bapak republik. Teringat kisah Thales yang jatuh ke sumur saat sedang asyik mengamati langit. Seringkali kita berpikir ndakik-ndakik tapi kita sendiri tidak menginjak tanah, pikiran kita tidak membumi. Kita lupa dengan kemerdekaan diri kita sendiri, kita abai dengan sekitar kita, tetangga kita yang kelaparan, saudara kita yang membutuhkan.
Pada akhirnya, peduli dengan orang terdekat kita lebih penting daripada kita hanya berteriak runtuhkan kapitalisme, turunkan bla-bla-bla. Kita tidak perlu menunggu Ratu Adil atau juru selamat yang akan membebaskan kita dari penindasan. Kita yang harus menjadi Ratu Adil. Masing-masing dari kita adalah juru selamat atas penindasan yang terjadi di sekitar kita. Di penghujung kata, penulis mengajak pembaca kembali merenung, tanyakan pada diri kita. Sudahkah kita merdeka 100%?.