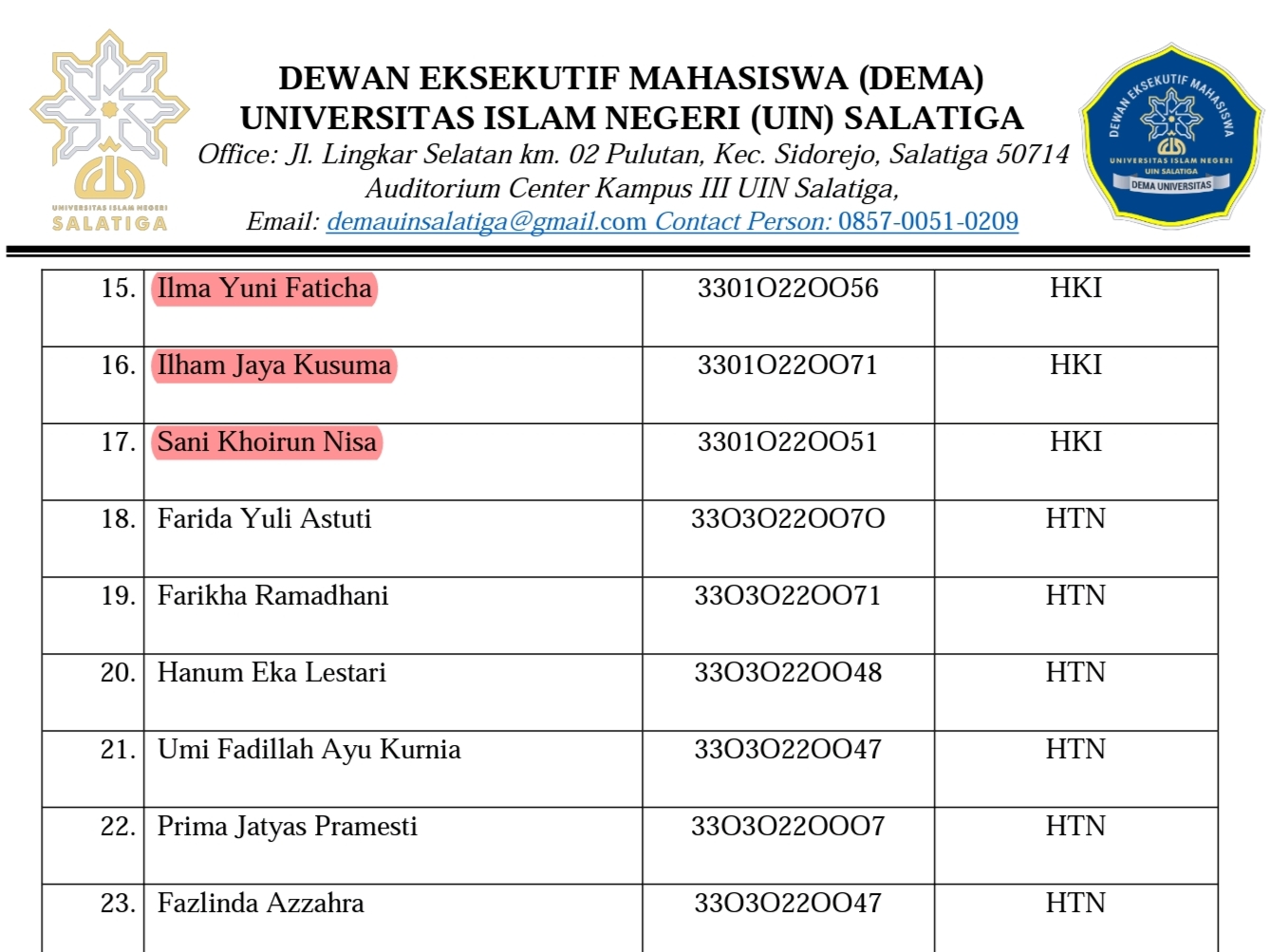Sumber Foto: Sky News
Oleh : Fatah Akrom
“Sepak bola lebih serius dari persoalan hidup dan mati” kutipan tersebut diambil dari Bill Shankly legenda Liverpool. Sepak bola tidak sesederhana sebuah olahraga semata, sepak bola punya dunianya sendiri dengan gerakan sosial, budaya bahkan intrik politik yang terbangun dalam sejarah panjangnya.
Tragedi yang terjadi di Stadion Kanjuruhan yang menewaskan setidaknya 125 orang menambah catatan kelam. Tragedi kerusuhan terbesar ketiga dalam sejarah sepak bola dunia. Dalam memandang sepak bola sebagian orang menganggap sepak bola adalah sebatas olahraga selama 90 menit atau sebuah permainan yang tidak terlepas dari menang dan kalah. Maka menjadi keheranan tersendiri jika sepak bola dapat mengambil nyawa orang yang menontonnya. Namun, harus kita akui sepak bola menjadi olahraga paling populer di muka bumi ini.
Sudah berapa juta anak di dunia ini yang bermimpi menjadi pemain sepak bola profesional, jutaan lainnya menggantungkan hidup pada sepak bola dan jutaan berikutnya sepak bola dianggap identitas atau harga diri sebuah kota atau negara yang patut untuk diperjuangkan. Kemunculannya tidak serta merta lahir begitu saja, sepak bola memiliki sejarah panjang dan rumit. Sepak bola modern mulai muncul ketika industrialisasi sedang mencapai puncaknya pada paruh abad ke-19 di Inggris. Kemudian dengan cepat tersebar seantero belahan dunia, lalu mengakar dan membentuk budaya dimana sepak bola tumbuh dengan subur.
Awal Mula Sepak Bola dan Budaya Kekerasan
Sejarah sepak bola tidak terlepas dari revolusi industri, kelas pekerja dan kekerasan. Jika ditinjau dari rumah sepak bola modern berasal, pada paruh abad 19 bisa dipastikan setiap kota industri maka disitu ada klub sepak bola. Ketika Liga Sepak Bola Inggris dimulai, setengah dari peserta liga berasal dari wilayah industri, mulai industri gelanggang kapal, perkeretaapian dan lain sebagainya. Tersebar di wilayah seperti Greater Manchester, Greater Merseyside dan Lancashire County. Hal tersebut juga dialami oleh kota industri Eropa lainnya seperti Milan, Turin, dan Catalonia. Kota tersebut memiliki karakter yang sama seperti kota Manchester karena dukungan dari para pekerja pendatang.

Mengutip tulisan dari laman Hooliganfc sepak bola mulai mendapatkan popularitas di Inggris pada abad ke-13. Pada waktu itu pertandingan sepak bola menampilkan pertandingan antar desa pada hari libur keagamaan. Dalam pertandingan tersebut bola yang digunakan berupa kandung kemih babi serta permainan yang kasar. Jauh sebelum sepak bola setenar sekarang Raja Inggris-Edward II sempat khawatir dengan permainan tersebut, karena dapat mengganggu ketenangan umum. Pada tahun 1314 Raja Edward II melarang masyrakatnya bermain sepak bola.
Kekhawatiran Raja Edward II terbukti ketika sepak bola Inggris terjadi aksi hooliganisme lebih dari lima abad kemudian. Sepak bola pada mulanya hanya sebuah hiburan murah bagi para pekerja lalu mulai menjelma menjadi fanatisme bahkan sampai ekstremisme dalam memberikan dukungan bagi klub sepak bola tertentu. Mereka lalu mengorganisir dan memiliki ikatan setiap anggotanya baik itu latar belakang ekonomi, budaya, agama, maupun ideologi. Sebut saja Hooligan di Inggris, Ultras di Italia, Barabravas di Argentina, Mania di Indonesia dan lain sebagainnya, menjadi hal yang tak terlepaskan dari budaya kekerasan di sepak bola.
Sebutan hooliganisme sendiri sudah ada sejak akhir era 1800-an, saat itu sebutan ini dipakai untuk suporter sepak bola saat perang dunia ke-2 yang kerap membuat onar. Ada beberpa teori menyebutkan asal usul kata hooligan ini berasal dari sebuah keluarga asal Irlandia yang tinggal di London. Mereka kerap berbuat rusuh yang kemudian menjadi inspirasi lahirnya kata hooligan. Keluarga tersebut memiliki nama Holy Hands yang terkenal dengan tindakan anarkisnya sehingga kata itu dipakai untuk menyebut nama penjahat.
Kebrutalan dan budaya berkelahi dalam sepak bola bukan hal baru. Merujuk pada latar belakang mayoritas suporter berasal dari kelas pekerja di Inggris. Kelas pekerja adalah kelas sosial yang banyak menggemari sepak bola karena relatif murah dari pada cricket atau berkuda yang menjadi tontonan elite pada waktu itu. Sejarah juga mencatat kelas pekerja adalah kelas sosial yang sering berkelahi di Inggris selama era 1800-an. Banyak terlihat perkelahian di sudut-sudut kota kecil di Inggris yang berkelahi karena mabuk, hal tersebut akibat menjamurnya banyak Bar.
Begitu juga Ultras di Italia, Ultras pertama kali muncul dalam sepak bola Italia pada periode 1960-an, istilah ini muncul sebagai bentuk perlawanan terhadap komersialisasi dan invasi kapitalisme dalam dunia sepak bola. Bentuk-bentuk perlawanan itu dimunculkan secara eksplisit dengan menonjolkan simbol-simbol kelompok, terutama simbol yang terafiliasi dengan ideologi politik tertentu, seperti swastika dan palu arit. Reputasi Barabavas di Amerika Latin juga cukup mentereng di kalangan pendukung sepak bola. Mereka merasa jauh lebih baik dari pada ultras dan hooligan di Eropa yang hanya mabuk dan bertengkar. Barabravas lebih rumit dibandingkan kebanyakan hooligan di Inggris yang kebanyakan adalah orang-orang yang mencari perkelahian di akhir pekan.
Sebagai sarana katarsis di Argentina Barabravas lebih memiliki hubungan dengan politisi, polisi dan manajemen klub. Pepe Diaz seorang Barabravas Boca Junior pernah mengungkapkan bahwa di Inggris kalian berpikir hooligan itu yang terkuat, tapi mereka tidak bisa dibandingkan dengan kami. Yang mereka lakukan adalah minum dan melawan. Kita minum, berjuang dan juga melakukan bisnis. Kami bukan hanya monyet-monyet yang bernyanyi untuk klub di stadion dan kemudian saling membunuh di jalananan. Mereka bisa belajar satu dua hal dari kami.
Dari Bisnis, Identitas, Politik bahkan Agama
“Kick Politics out of football.” Ungkapan ini sering kita dengar dalam sepak bola modern, tapi apakah hal tersebut bisa benar-benar terjadi? Dalam perkembangannya sepak bola sedari dulu menjadi ruang memperjuangkan ekspresi politik dari paling kiri hingga paling kanan. Bahkan tidak sedikit klub sepak bola berdiri atas tujuan politik. Jadi, tak ayal sepak bola dapat menggerakkan massa yang besar dan suporter menjadi hal yang sangat sakral. Sampai sakralnya lebih dari ratusan klub mempensiunkan angka 12 sebagai wujud penghormatan terhadap suporter.
Bisnis sepak bola adalah hal yang menggiurkan. Signal Iduna Park adalah contoh kesempurnaan bagaimana sebuah klub mengakomodasi keuntungan suporter. Kapasitas stadion milik Borussia Dortmund 80.000 penonton dengan lebih 24.000 penonton tanpa tempat duduk dikhususkan untuk suporter fanatik Dortmund, di kenal dengan nama The wall. Maka tak dipungkiri jika ada segelintir orang akan tidak jauh dari bisnis dan politik kepentingan untuk kelompok tertentu.

Seperti halnya Barcelona mempunyai slogan yang sangat kontra dengan Real Madrid, “Kita boleh kalah dengan siapa saja, tapi tidak dengan Madrid”. FC Barcelona adalah ideologi dan simbol perlawanan bangsa Catalan, seharusnya perlawanan mereka tertuju pada bangsa Castilan dan klub-klub sepak bola pendukung kerajaan Spanyol seluruhnya. Hal tersebut terjadi karena Real Madrid adalah klub dari ibukota Spanyol. Klub dari ibukota Spanyol tidak hanya Real Madrid, ada Atletico Madrid sebuah klub Angkatan Udara yang dalam sejarahnya tentara yang membantai penduduk Catalan saat perang saudara.
Tapi rivalitas Barca dengan Atletico tidaklah sekental dengan El Real. Arti kata Real dan simbol mahkota di atas lambang klub ibu kota tersebut memiliki sejarah dimana pada awal berdirinya, tidak ada nama Real pada klub ibu kota ini, hanya Madrid FC. Penambahan kata ‘Real’ pada awalan klub ini diberikan oleh Raja Spanyol, Alfonso XIII pada tahun 1920 seperti pemberian sebuah gelar the royal (bangsawan) bagi klub yang mewakili hegemoni sang Raja tersebut.
Bahkan konflik agama menjadi bumbu penyedap di sepak bola Israel, Hapoel Tel Aviv berdiri sejak 1923 yang sangat dekat dengan kaum kelas pekerja. Hapoel sendiri berarti pekerja yang dari namanya sudah menggambarkan haluan politiknya, mereka menentang rasisme dan zionisme. Di liga Israel, Hapoel punya rival abadi yaitu Beitar Jerusallem FC yang justru sangat rasis dan fasis. Mereka tak pernah mau menerima pemain berkulit hitam, muslim atau berketurunan Arab. Pernah di tahun 2013 menolak keras 2 pemain baru muslim yang langsung diprotes keras. Berbeda dengan Hapoel yang terbuka untuk semua negara dan agama, mereka anak semua bangsa. Tak hanya di Stadion Hapoel juga mengambil andil dalam demontrasi jalanan bersama buruh dengan menyuarakan isu feminis dan lingkungan.
Sepak Bola, Mulai dari Menghentikan Perang Sampai Menggerakkan Arab Spring

“Football its not just a simple game, its weapon of the revolution,” ungkapan tersebut dikutip dari Che Guevara. Dalam perkembangannya sepak bola bukan cuma hal kotor dan alat politik. Karena jikalau memang sepak bola adalah hal yang merusak ia tidak akan pernah bertahan berabad-abad lamanya, tak akan pernah kering cerita mengenai sepak bola. Didier Drogba memiliki reputasi yang begitu hebat sepanjang kariernya bermain sepak bola, menjadi legenda Chelsea setelah mengabdi di Stamford Bridge selama sembilan tahun. Sang legenda sepak bola Pantai Gading mampu menghentikan perang saudara yang berkecamuk di negara asalnya.
Seperti yang dilaporkan oleh BBC pada tahun 2005, Drogba bermain untuk Pantai Gading melawan Sudan dalam ajang kualifikasi Piala Dunia 2006. Mereka wajib meraih hasil yang lebih baik dari pesaing terdekat, Kamerun yang melawan Mesir pada malam yang sama, untuk bisa melaju. Pantai Gading memenangkan laga tersebut. Setelah peluit panjang dibunyikan, Kamerun ditahan imbang 1-1 oleh Mesir, dengan hanya beberapa menit tersisa dan mendapatkan penalti. Beruntung bagi Drogba dan kawan-kawan, penyerang Kamerun, Pierre Wome gagal mengeksekusi penalti, sehingga memungkinkan Pantai Gading lolos ke Piala Dunia untuk pertama kalinya dalam sejarah mereka.
Setelah laga usai Drogba lalu berpidato. “Masyarakat Pantai Gading. Dari utara, selatan, tengah dan barat, kami membuktikan hari ini bahwa semua warga Pantai Gading dapat hidup berdampingan dan bermain bersama dengan tujuan yang sama, untuk lolos ke Piala Dunia,” ujarnya penuh ketegasan. “Kami berjanji kepada anda bahwa selebrasi akan menyatukan semua orang -hari ini kami memohon kepada kalian,” lanjutnya sembari diikuti para pemain yang berlutut. “Satu negara di Afrika dengan begitu banyak kekayaan tidak boleh jatuh ke dalam perang. Tolong taruh senjata kalian dan adakan pemilihan,” para pemain kemudian bangkit dan bersorak. “Kami ingin bersenang-senang, jadi berhentilah menembakkan senjata kalian!,” tegasnya.
Pidato Drogba itu memiliki efek yang sangat besar, akhirnya membantu dua kubu yang berperang naik ke meja perundingan, gencatan senjata akhirnya ditanda tangani. Setahun berselang, Drogba mengatakan bahwa pertandingan internasional melawan Madagaskar akan diadakan di utara Pantai Gading. Bouake, wilayah yang dulunya dikuasai oleh pemberontak. Laga tersebut digelar pada tahun 2007, Pantai Gading menang dengan skor 5-0 atas Madagaskar. Drogba yang turut mencetak gol pada akhir pertandingan diarak keliling lapangan. Momen tersebut kian menyatukan masyarakat Pantai Gading.
Kekuatan sepak bola adalah satu-satunya olahraga yang memiliki inner power untuk membangkitkan kebersamaan dalam melakukan perlawanan entah digunakan untuk revolusi atau kudeta, apa yang diucapkan Che Guavara ada benarnya tentang bagaimana sepak bola menjadi motor penggerak Revolusi Mesir. Walaupun fenomena ultras masih baru di Mesir, keberadaan ultas berawal dari tak mampunya partai oposisi menyuarakan haknya.
Noam Chomsky dalam buku “Media Control The Spektakuler Achievement Of Propaganda” memaparkan sepak bola adalah cara efektif untuk meredam kaum pandit terlibat aktif dalam politik. Teori inilah yang diadopsi oleh rezim Husni Mubarak sampai muncul anekdot “satu-satunya ruang kritis dimana orang bisa mengekspresikan diri adalah Ikwanul Muslimin di masjid dan Ultras di stadion sepakbola”. Suporter di Mesir adalah organisasi independen, mereka hadir saat kebebasan berserikat diberantas habis oleh rezim Mubarok.
Arabian Spring melanda Mesir di penghujung tahun 2010 membuat ultras akhirnya turun ke jalan dan keluar dari jalurnya sebagai suporter. Mereka bergabung bersama jutaan rakyat Mesir lainnya dalam revolusi 25 Januari. Mereka memaksa mundur Husni Mubarak yang keotoriteriannya sudah berlangsung selama 30 tahun dengan cara memanfaatkan militer dan membuat demokrasi yang semu. Jika rezim memasang tentara dan polisi sebagai tameng depan maka ultras lah garda terdepan melindungi demonstrasi rakyat.
Namun, perjuangan para ultras di luar lapangan ini harus dibayar mahal saat rezim Husni Mubrak jatuh. Dikarenakan kejatuhannya tidak diiringi antek-anteknya yang masih bercokol dalam jajaran petinggi pejabat militer. Puncak ketidaksukaan rezim terhadap ultras harus di bayar Ultras Al-Ahly dalam tragedi Port Said 2012 silam. Kala itu 74 orang tewas dan 1.000 orang terluka akibat kerusuhan antara Ultras Ah-Ahly dengan Al-Masry. Hal tersebut diyakini secara luas bahwa militer ingin memberikan ultras pelajaran serta sebagai gerakan kontra revolusi.
Salah Langkah Modernisasi Sepak Bola di Indonesia
Budaya Hooligan dan Ultras terus berkembang dan sampai di Indonesia. Globalisasi hooligan dan ultras yang begitu cepat menjadi faktor munculnya budaya tersebut. Hendika dan Nuraini dalam artikelnya yang berjudul “Globalisasi Hooliganisme Terhadap Suporter Sepakbola di Indonesia” yang dimuat di Jurnal Hubungan Internasional tahun 2020 menyebutkan bahwa para suporter sepak bola di Indonesia mulai meniru segala tindakan yang mereka temui melalui internet dan televisi.
Mereka menerapkannya dengan cara memberikan dukungan kepada klub yang mereka dukung. Suporter sepak bola Indonesia mulai meniru gaya berpakaian Hooligan ketika menonton langsung pertandingan di stadion, gaya berpakaian yang kasual yang sangat digemari anak muda serta nilai militansi di luar batas kewajaran. Namun, sialnya budaya negatif seperti tradisi mabuk dan berkelahi mereka tiru walaupun sebelum fenomena ini kerusuhan sudah sering terjadi di Indonesia.

Misalnya dalam rivalitas antara suporter PSIM Yogyakarta yaitu Brajamusti dengan suporter Persis Solo yakni B6 juga kerap terjadi tindakan anarkis bahkan sampai saat ini. Derby Mataram tidak kalah panas dari pertandingan Persib Bandung vs Persija Jakarta. Kebencian suporter Persis lahir dari tragedi balas membalas yaitu Tragedi Menjangan 1998 dan Tragedi Mandala Krida tahun 2000. Kedua suporter hingga kini belum berdamai dan sering terjadi aksi saling sweeping dari kedua belah pihak. Jika kultur hooligans dan ultras tidak segera ditangani serius kerusuhan-kerusuhan besar akan terjadi dimanapun dan kapanpun. Kerusuhan yang terjadi bukan hanya persoalan sepak bola namun merambah ke persoalan lainya seperti rasisme kesukuan, budaya, maupun sosial. Tensi yang panas serta dendam yang berkepanjangan akan mudah membuat mereka berbuat anarkis.
Masyarakat Indonesia merasa lelah dan tidak dapat berharap banyak dari federasi sepak bola di negeri ini. Jangankan memgusut tuntas dalam mengurus tragedi demi tragedi. Konflik internal berkepenjangan, perebutan kursi kekuasaan, mafia bola, pengaturan skor, profesionalitas wasit, sepak bola gajah, dan seabrek pekerjaan rumah lainnya menjadi masalah dan sudah jadi rahasia umum. Sepak bola modern di Indonesia akan menjadi dua mata pisau yang sama-sama berbahaya bagi federasi.
Suporter bisa mulai belajar dan berbenah, maka itu akan menjadi alat oposisi yang kuat untuk merombak secara menyeluruh. Namun, jika budaya kekerasan ini dibiarkan maka budaya itu akan merebak bak jamur di musim penghujan dan sulit untuk dikendalikan. Sampai akhir tulisan saya ini, sepak bola tidak pernah kering dalam memberikan kisah-kisahnya yang melumpuhkan logika. Ia akan tetap menggelinding menyusuri lerung waktu pemain, penonton dan seluruh masyarakat.