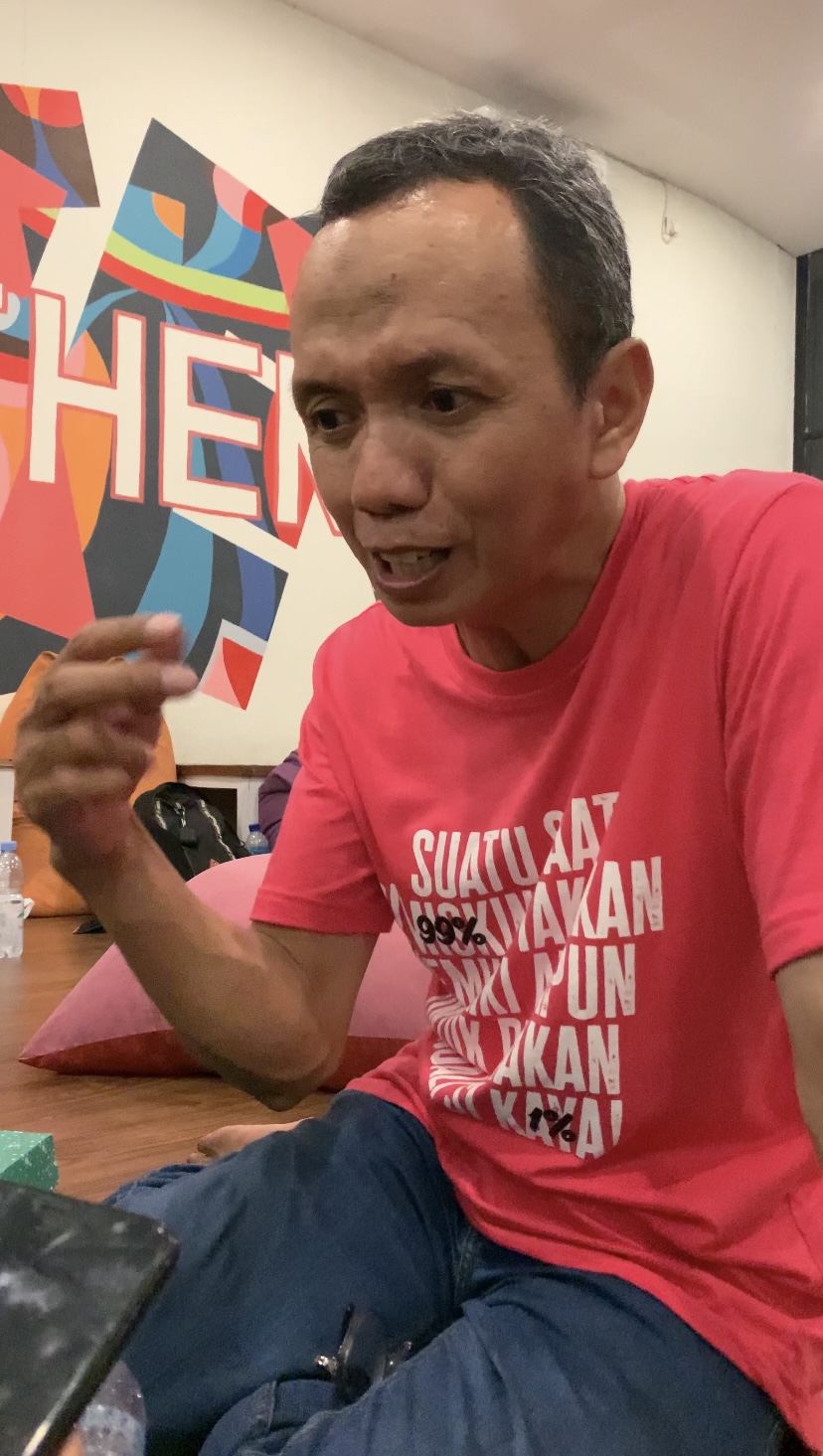Sosok Suciwati, istri mendiang Munir (ketiga dari kanan), yang menyuarakan ketidakadilan atas kasus pembunuhan suaminya dalam Diskusi Akbar “Cak Munir Adalah Kita” (Sumber Foto: Mada/DinamikA).
Klikdinamika.com–Tercatat pada 7 September 2004 di langit Rumania, menjadi akhir perjalanan hidup Munir Said Thalib—seorang pembela Hak Asasi Manusia (HAM). Racun arsenik ditemukan dalam jus jeruk yang diminumnya di pesawat menjadi tanda akhir penyebab ia meninggal. Hingga sekarang, hal tersebut masih menyimpan tanda tanya besar. Alasan mengapa Munir dibunuh dan siapa dalang utama pembunuhan belum terungkap secara jelas. Selama pelaku pembunuhan belum terungkap, keadilan untuk kasus pembunuhan masih jauh dari kata tuntas.
Suciwati, istri Munir, sampai saat ini masih lantang menyuarakan kisah-kisah mendiang suaminya. Selama 20 tahun mengenang sosok Munir, lewat acara ‘Cak Munir Adalah Kita” reporter Klikdinamika.com berkesempatan menghampiri Suciwati, seorang perempuan kuat yang masih memperjuangkan keadilan atas keluarganya, Kamis (26/9/2024).
Bagaimana sosok Munir di mata anak-anak, terutama dalam keluarga?
Anak-anak masih merasakan kehilangan yang sangat dalam, terutama Alif–anak pertama kami. Mereka kehilangan sosok ayah yang begitu perhatian, penyayang, dan penuh kebaikan. Munir bukan hanya ayah yang baik, tetapi juga sangat peduli terhadap kebutuhan anak-anaknya. Misalnya, dulu dia selalu mengantar mereka sekolah, memandikan, bahkan menyuapi ketika mereka masih kecil. Kehilangan sosok seperti itu jelas meninggalkan luka yang dalam.
Apa pengaruh kepergian Munir terhadap keluarga, khususnya bagi Ibu dan anak-anak?
Pengaruhnya sangat signifikan. Kami kehilangan seorang yang menjadi pasangan hidup, sosok yang memberi nafkah, baik secara jasmani maupun rohani. Kehilangan Munir tidak hanya dalam ruang privat, tapi juga sebagai teman diskusi, tempat berbagi suka dan duka. Di ruang aktivisme, saya juga merasa kehilangan sosok yang berani, vokal, dan memiliki moralitas yang sangat tinggi. Anak-anak pun kehilangan ruang-ruang diskusi, kebersamaan, dan parenting yang seharusnya ada.
Bagaimana awal pertemuan Ibu dengan Munir dan kesan pertama terhadap beliau?
Mengenal Munir adalah anugerah. Saat pertama kali bertemu, dia adalah sosok anak muda yang luar biasa, tidak kenal lelah. Hidupnya didedikasikan untuk membantu orang-orang yang tertindas. Waktu itu, saya sedang mengorganisir buruh di Malang, dan Munir sangat tertarik dengan advokasi buruh. Bahkan, ketika Marsinah dibunuh, dia yang mengadvokasi kasus tersebut. Munir selalu berada di garis depan dalam membela mereka yang terpinggirkan.
Bagaimana kebiasaan-kebiasaan Munir yang mungkin tidak banyak diketahui orang?
Munir itu sederhana sekali. Dia lebih suka naik motor ke mana-mana daripada mobil. Pakaian pun harus dibeli di pasar, bukan di mal. Alasannya, dia ingin memperkuat masyarakat sipil dan ekonomi rakyat, bukan kapitalis. Kesederhanaannya begitu kuat, bahkan teman-teman aktivis sering menggoda bahwa “nanti Munir sikat gigi pakai batu bata”. Tapi itu karena idealisme yang sangat melekat pada dirinya. Dia juga selalu menolak tawaran dari orang-orang kaya, entah itu ditawarin rumah atau jabatan, karena kami bangga hidup mandiri, tidak berhutang budi pada siapapun.
Bagaimana Munir menghadapi tantangan dalam hidupnya, terutama dalam menjalani profesinya sebagai aktivis?
Munir itu selalu siap menghadapi risiko dalam pekerjaannya. Ketika mengadvokasi peristiwa 27 Juli 1996, dia menjadi korban kekerasan hingga tulang tangannya patah. Meskipun harus dioperasi, dia memilih diobati oleh dokter yang dekat dengan teman-teman aktivis. Itu salah satu contoh bagaimana dia mengorbankan dirinya untuk memperjuangkan keadilan.
Bagaimana Munir dan Ibu menghadapi tantangan ketika mengetahui kondisi kesehatan anak, terutama saat didiagnosis autisme?
Tahun 1998, kami memiliki anak dan pada tahun 2000, dokter mendiagnosis anak kami, Alif, dengan autisme. Autisme memerlukan biaya yang tidak sedikit untuk terapi, suplemen, dan perawatan lainnya. Dengan gaji Munir yang hanya sekitar Rp 750.000,- tentu sulit untuk memenuhi semua kebutuhan tersebut. Tapi kami selalu berpegang teguh pada prinsip hidup mandiri, tidak bergantung pada orang lain. Bagi kami, kebanggaan sejati adalah hidup dari hasil jerih payah sendiri, tanpa pemberian atau bantuan dari pihak lain. Munir bagi saya seperti sosok yang dikirim oleh Tuhan, tidak hanya untuk saya, tetapi juga untuk bangsa ini. Dia mampu membangkitkan semangat perlawanan, terutama di kalangan anak muda. Munir pernah berkata, “Kalau aku menghadapkan wajahku kepada Tuhan, maka aku harus membela orang lain”. Itu adalah semangat hidupnya.
Bagaimana Munir dididik di masa kecil dan mudanya, yang membentuk keberaniannya dalam memperjuangkan keadilan?
Sejak kecil, Munir sudah dididik dalam ruang kemandirian. Dia dibesarkan sebagai seorang pedagang, karena menjadi pedagang itu independen. Ketika menjadi mahasiswa, dia sempat terlibat dalam konflik ideologi—satu kelompoknya masuk ‘ijo’ (mendukung kelompok tertentu), sementara yang lain ‘merah’. Tapi seiring berjalannya waktu, Munir merasa, “Apaan sih ini?” Akhirnya, dia memilih untuk menjadi sosok yang berani melawan ketidakadilan. Keberanian itu adalah sebuah pilihan, bukan sesuatu yang datang begitu saja. Kita bisa memilih untuk terus ditindas, atau kita memilih untuk bersuara, berteriak, dan melawan ketidakadilan. Munir memilih untuk melawan
Bagaimana Ibu melihat peran generasi muda yang mencoba melanjutkan perjuangan Munir melalui acara-acara diskusi semacam ini?
Acara-acara seperti ini harus diperbanyak. Diskusi, baik dalam skala kecil maupun besar, sangat penting. Generasi muda harus terus membangun idealisme dan semangat pergerakan. Munir adalah sosok yang berani melawan ketidakadilan. Rezim yang memabukkan bisa membuat kita lupa, tapi anak muda harus lebih kreatif dan berani. Kuncinya adalah semangat seperti Munir: muda, berani, dan siap melawan. (Joysi/red)