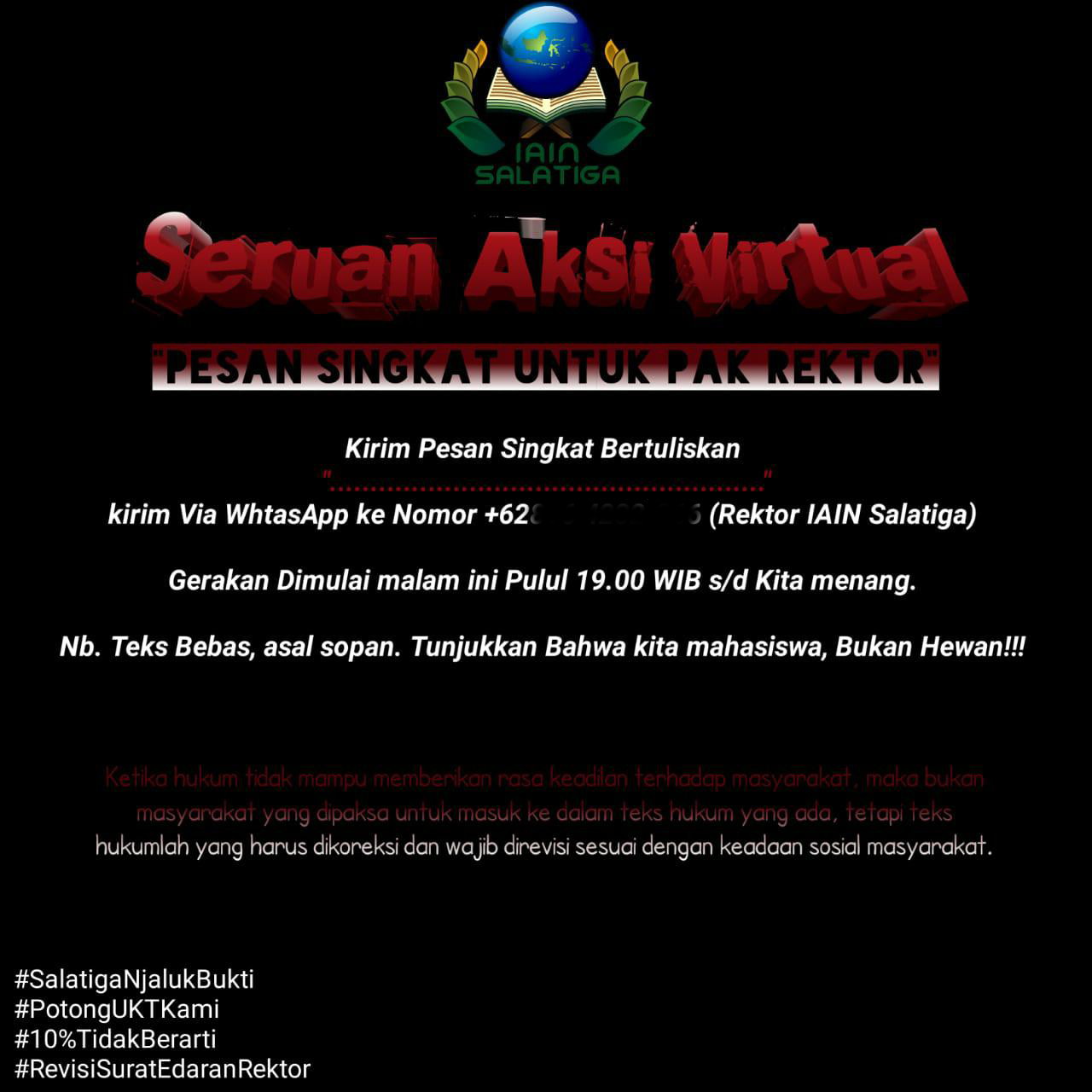Sumber Foto: aktulalitas.id
Oleh: Faiz Alfa
Formalisasi syari’at Islam di tingkat provinsi sudah menjadi wacana di berbagai daerah di Indonesia. Wacana ini berkembang di daerah yang mayoritas penduduknya beragama Islam, seperti Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Sumatera Barat. Gagasan yang bertujuan memberlakukan syari’at Islam dalam Peraturan Daerah ini tidak hanya berkembang di kalangan elit muslim atau ulama saja, melainkan juga ramai dibicarakan di tingkat umat awam atau akar rumput.
Dikhawatirkan, wacana tersebut berpotensi menimbulkan beberapa dampak buruk bila benar-benar direalisasikan. Dampak buruk itu akan sangat terasa, di kemudian hari, di daerah bermayoritas non-muslim seperti Provinsi Papua dan Sulawesi Utara.
Ketika daerah-daerah bermayoritas muslim merealisasikan formalisasi syari’at Islam, maka tidak menutup kemungkinan akan terjadi formalisasi syari’at non-islam di daerah bermayoritas non-muslim, seperti yang terjadi di Manokwari, Papua Barat. Mungkin ini sebatas asumsi liar, namun tidak menutup kemungkinan akan terjadi.
Hal itu baru satu di antara beberapa dampak buruk yang mungkin terjadi. Belum lagi kerentanan konflik horizontal yang akan timbul. Konflik ini dapat terjadi antara golongan muslim dengan non-muslim bahkan antar sesama muslim. Di sini, penulis ingin mengajak pembaca untuk membicarakan dua kekhawatiran tersebut.
Kekhawatiran Pertama: Sebuah Asumsi Liar
Misalnya, daerah-daerah yang bermayoritaskan muslim seperti Sumatera Barat dan Nusa Tenggara Barat menerapkan syariat Islam secara total dalam Peraturan Daerah (Perda) mereka. Konsekuensi logisnya adalah kepatuhan yang wajib dilakukan seluruh penduduk daerah-daerah itu, tanpa terkecuali, termasuk mereka yang non-muslim. Hal ini terjadi di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
Melihat fenomena itu, daerah-daerah bermayoritas penduduk non-muslim akan terpancing untuk mekakukn hal serupa. Kalau orang Islam membuat Perda berdasarkan ajaran Islam di daerah yang mana mereka menjadi mayoritas di sana, maka orang kristen juga boleh melakukan hal serupa. Daerah bermayoritas kristen seperti Sulawesi Utara dan Papua kemudian dapat melakukan formalisasi ajaran Kristen di sana, dengan bentuk membuat Perda berdasarkan ajaran Kristen. Hal ini sudah terjadi di Manokwari, Papua Barat.
Akibat dari hal ini adalah tuntutan untuk mengakui dan mematuhi peraturan yang telah dibuat. Semua penduduk Sulawesi Utara, tanpa terkecuali, harus mengakui bahwa peraturan itu sah dan legal. Selain itu, mereka semua, termasuk muslim juga harus mematuhi peraturan yang notabene ajaran Kristen itu.
Mungkin, umat Kristen di Sulawesi Utara tidak terlalu mempersoalkan kewajiban yang menimpa mereka, yaitu mengakui dan mematuhi Perda yang pada esensinya adalah syariat Kristen. Namun, suatu hal yang bertolak belakang akan terjadi di pihak umat Islam. Mereka cenderung akan tidak terima apabila dituntut untuk mengakui dan mematuhi Perda yang pada esensinya berbeda dengan ajaran mereka. Hal ini bukan tanpa alasan, sebagian besar dari mereka menganggap bahwa: mematuhi hukum agama lain sama dengan melakukan kekafiran.
Anggapan ini timbul dari pemahaman literal atas sebuah hadist yang masih diperdebatkan ke-shahih-annya, yaitu: barang siapa yang tidak menetapkan hukum berdasarkan Al-Qur’an, maka dia adalah orang kafir (wa man lam yakhkum bimaa anzalallahu fa-ulaaika hum al-kaafiruun).
Kekhawatiran Kedua: Konflik Horizontal
Rasa tidak terima itu sangat mungkin menimbulkan efek berkepanjangan yang menjalar ke mana-mana. Suara penolakan terhadap Perda Kristen dari umat muslim akan merebak. Belum lagi umat muslim dari daerah-daerah lain yang ikut mendukung aksi mereka atas dasar solidaritas. Di kubu lain, umat Kristen menyuarakan pembelaan tersebut atas dasar keadilan. Apalagi kalau dua kubu saling berhadapan-hadapan secara fisik, kerusuhan seperti yang pernah terjadi di Poso dan Ambon bukan tidak mungkin terulang kembali.
Konflik horizontal akan menimbulkan banyak kerugian yang bersifat material dan non-material. Dalam bentuk material, kerugian bisa dilihat pada kerusakan yang terjadi pada benda-benda fisik seperti bangunan dan fasilitas umum. Selain benda fisik, kerusakan pada manusia seperti luka-luka, kecacatan dan kematian juga bisa terjadi.
Dalam bentuk non-material, kerugian itu bisa dilihat pada aspek manusianya, tentu manusia yang terdampak konflik. Contohnya adalah trauma yang dialami oleh korban. Selain itu, watak anggota masyarakat juga bisa berubah secara drastis. Semua hal tersebut adalah buntut panjang dari sebuah kebijakan yang kemudian menimbulkan perdebatan dan pada akhirnya menjadi chaos.
Meski begitu, situasi konflik memiliki sisi positif juga. Salah satunya adalah menghasilkan generasi kuat. Hal tersebut adalah sebuah adagium lama yang diyakini banyak orang, bahwa situasi krisis akan menghasilkan generasi yang kuat. Generasi yang kuat itu akan menghasilkan peradaban yang maju. Selain itu, ada adagium lain yang mengatakan bahwa, pada situasi krisis, seorang pemimpin kharismatik akan muncul.
Paradigma Alternatif
Menurut Abdurrahman Wahid (Gus Dur), dalam sejarah perumusan pancasila, terdapat tujuh kata yang dihapus, yaitu “Kewajiban menjalankan syari’at Islam bagi para pemeluknya.” Penghapusan ini disetujui oleh tokoh-tokoh Islam yang mewakili golongannya, seperti A. Kahar Mudzakir (Muhammadiyah), Abi Kusno Cokrosuyoso (Sarekat Islam), A. Rahman Baswedan (Partai Arab Indonesia/PAI), Ahmad Subarjo (Masyumi) dan Wahid Hasyim (NU). Mereka sepakat tentang dampak negatif yang mungkin terjadi bila tujuh kata itu dipertahankan.
Dari sekian juta penduduk muslim di Indonesia, mereka yang menjalankan syariat Islam secara tuntas baru 30 persen. Selebihnya kurang atau bahkan tidak taat dalam menjalankan syari’at Islam. Inilah yang membuat para founding fathers menerima penghapusan tujuh kata dalam pancasila.
Dari sini, terlihat bahwa para “bapak bangsa” mengambil langkah yang berbanding terbalik dengan wacana formalisasi syari’at Islam. Mereka menghapus bagian yang memperlihatkan syari’at Islam secara formal di dalam sumber hukum. Sedangkan, wacana ini malah ingin menambahkan sesuatu yang menampakkan ajaran Islam secara formal dalam hukum yang seharusnya merujuk pada sumber hukum, yaitu pancasila. Tindakan ini dalam peribahasa Jawa disebut ‘mindoni gawe.’
Selain itu, perlu kiranya mengutip pernyataan dari Sujiwo Tejo yang cukup menarik. Menurutnya, formalisasi syari’at Islam seharusnya dilakukan secara bottom-up (dari bawah ke atas), bukan top-down (dari atas ke bawah). Maksudnya, biarkan nilai-nilai Islam di masyarakat tumbuh dan mengakar kuat terlebih dahulu, baru kemudian hukum islam itu dibuat secara formal dalam undang-undang atau peraturan. Bukan sebaliknya, membuat peraturan Islam dahulu dengan harapan masyarakat akan menaatinya.
Dia juga memberi amsal yang cukup menghentak. Bahwa ketika ramai-ramai wacana formalisasi hukum islam, dia jarang sekali atau bahkan tidak menemukan tempat kencing duduk untuk pria di SPBU. Semuanya berdiri. Tempat kencing itu tidak jarang menghadap atau membelakangi kiblat. Hal ini, baginya, tidak islami. Maksud dari amsal ini adalah sebuah fakta bahwa masyarakat belum siap menerima itu dengan kesehariannya sekarang.
Akhir kata
Melihat dampak buruk yang akan terjadi dan statistik ketaatan umat Islam di Indonesia, maka akan lebih produktif apabila formalisasi syari’at Islam secara total tidak diterapkan di tingkat daerah. Syari’at Islam boleh, bahkan memang sudah seharusnya, dianggap sebagai ajaran yang akan membawa dampak positif bagi orang yang menerapkannya. Hanya saja, sebuah keputusan yang berangkat dari pemahaman tekstualis-literal dan dilakukan secara menggebu-gebu akan berdampak pada efek buruk yang berkelanjutan. Maka dari itu, umat Islam–yang dalam hal ini diwakili oleh elit-elitnya yaitu ulama–harus beranjak dari cara pandang tekstual menuju cara pandang kontekstual.
Pada akhirnya, bagian dari syari’at Islam yang nantinya ditampilkan dalam Perda bukan kulitnya, tapi nilai (value) yang termuat di dalamnya. Penulis yakin bahwa nilai yang terkandung dalam syari’at Islam cenderung bersifat universal. Sehingga sangat mungkin nilai-nilai itu juga terkandung di dalam ajaran agama lain, seperti Buddha, Hindu dan Kristen. Apabila benar-benar diterapkan, maka yang akan terjadi adalah keseimbangan (harmony) yang sesuai dengan tujuan-tujuan ajaran Islam (maqashid asy-syari’ah).
Referensi
Abdurrahman Wahid, Islamku Islam Anda Islam Kita: Agama Masyarakat Negara Demokrasi, (Jakarta: The Wahid Institute, 2006), hal. 21-24.
Masnun Tahir, Tuan Guru dan Dinamika Hukum Islam di Pulau Lombok, (Jurnal Asy-Syir’ah Vol. 42 No. I, 2008), hal. 86-115.
Sujiwo Tejo saat memberikan statemen dalam program “Indonesia lawyers Club” di TVOne, 21 Agustus 2022, (https://www.youtube.com/watch?v=llpZoaQ7F3w).
Al-Qur’an, 5:44