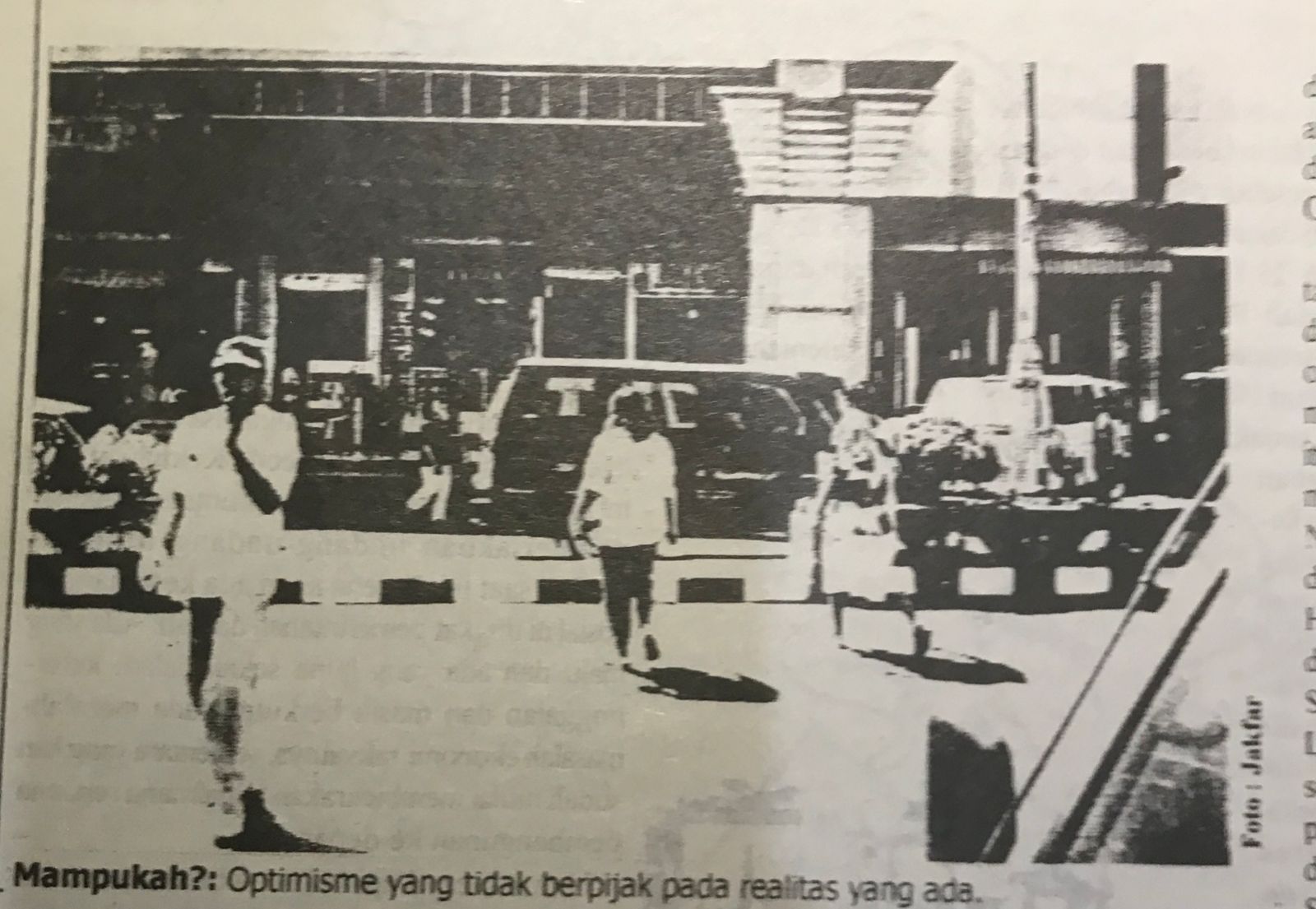Sumber Foto: Arsip DinamikA
Oleh: Muhammad AS Hikam*
Rubrik Artikel dalam Majalah DinamikA “Pemimpin Indonesia Mendatang Where You Will Come From?” Edisi ke-19 Tahun 1999
Gerakan reformasi yang berkembang di tanah air kita, saat ini sedang berada pada sebuah fase atau tahapan paling krusial–yang akan menentukan apakah ia akan benar-benar menghasilkan sebuah perubahan fundamental dan menyeluruh dalam tata kehidupan politik, ekonomi, hukum, dan sosial ataukah sebaliknya. Fase tersebut ditandai dengan beberapa pertarungan, antara beberapa kekuatan yang ingin muncul sebagai kekuatan dominan yang pada gilirannya nanti akan menjadi penentu fase penataan dan normalisasi di masa depan. Dalam fase yang sekarang, kekuatan-kekuatan yang sedang bertanding terdiri atas kekuatan sisa reim lama (the ancient regime) di satu pihak dan berbagai kekuatan pembaharu dalam masyarakat di lain pihak.
Dalam kondisi seperti ini, maka terjadi tarik ulur, konsesi-konsesi, dan perebutan perebutan posisi politik dari masing-masing kekuatan, sampai pada akhirnya terjadi semacam kristalisasi kekuatan-kekuatan yang kemudian muncul sebagai pemenang akhir. Mungkin saja, kekuatan terakhir ini terdiri atas satu koalisi yang berisi sebagai kekuatan politik, tetapi juga bukan tidak mungkin hanya satu kekuatan dominan. Demikian pula, bisa saja kekuatan baru tersebut akan berwujud kekuatan reformatif, tetapi bukan tak mungkin yang muncul adalah kelanjutan atau metamorphose dari rezim lama.
Dengan demikian, sangatlah urgen kiranya untuk mencermati serta menyikapi secara
kritis proses yang sedang terjadi pada fase ini. Apalagi jika kita menginginkan hasil dari reformasi menyeluruh adalah munculnya sebuah bangunan sistem politik, yang dapat menopang proses demokratisasi serta dapat menjadi wahana bagi pemberdayaan civil society. Untuk keperluan tersebut, tulisan pendek ini mencoba mendiskusikan proses reformasi yang sedang berjalan dan prospek pemberdayaan civil society dalam konteks pertarungan kekuatan-kekuatan politik yang ada dewasa ini. Dalam tulisan ini, pertama-tama akan dipaparkan kondisi civil society di bawah rezim lama dan persoalan-persoalan apa saja yang dihadapi dalam rangka melakukan pemberdayaannya. Setelah itu, akan didiskusikan kemungkinan reformasi yang sedang berlangsung apakah akan berdampak positif atau negatif, dan akhirnya bagaimana upaya-upaya pemberdayaan di masa depan terlepas dari reformasi berhasil atau gagal.
Kondisi Civil Society di Bawah Rezim Orde Baru
Sebagaimana yang kita ketahui dari pengalaman kesejarahan dari bangsa bangsa yang telah maju dan demokratis, keberadaan civil society yang kuat dan mandiri merupakan salah satu landasan pokok bagi ditegakkannya sistem politik demokrasi. Civil society di sini diartikan sebagai wilayah kehidupan sosial yang terorganisasi, dengan ciri-ciri kesukarelaan, keswadayaan, keswasembadaan dan kemandirian berhadapan dengan negara. Dengan tumbuh dan berkembangnya civil society yang kuat dan mandiri, dimungkinkan terwujudnya kemampuan mengimbangi dua kekuatan yang cenderung intervensionis, yaitu negara dan pasar. Dengan berkembangnya civil society yang kuat, maka dimungkinkan pencegahan terhadap dampak-dampak negatif dari dua kekuatan tersebut. Sehingga, kehidupan demokratis tetap terjaga. Dari pihak negara, kemungkinan monopoli atau dominasinya akan mengakibatkan hilangnya kemandirian pribadi atau merosotnya karsa karsa bebas di dalamnya–yang sebetulnya sangat penting bagi kehidupan demokrasi. Dampak negatif dari negara yang terlalu intervionis adalah: ketergantungan yang sangat tinggi dari kelompok-kelompok dalam masyarakat dan pribadi-pribadi kepadanya. Akibatnya, bukan saja masyarakat menjadi kehilangan semangat (elan) vitalnya, tetapi negara sendiri pada akhirnya harus menanggung beban terlalu berat sehingga rentan terhadap krisis.
Sementara, dampak negatif dari kekuatan ekonomi pasar adalah: atomisasi dan pasifikasi masyarakat yang mengakibatkan memudahkan perekatnya komunitas. Kapitalisme yang pada intinya menuntut individu dibebaskan sepenuhnya agar dapat mencari kepuasan, pada gilirannya mendorong terjadinya kompetisi yang tidak sehat di dalam masyarakat. Tidak hanya itu, kapitalisme juga memungkinkan melebarnya jurang yang memisahkan si miskin dengan si kaya. Sistem politik yang mengabaikan kenyataan seperti ini dan tidak mampu melakukan pengawasan atasnya, kendatipun di luar tampak demokratis. Tetapi, di dalam sejatinya mengidap penyakit kronis; alienasi kaum lapis bawah dan kelangkaan partisipasi dari mereka.
Sebab hal itu, untuk mengurangi dan mengantisipasi ekses-ekses tersebut civil society menjadi sangat penting. Dia dapat menjadi benteng yang menolak intervensi negara yang berlebihan melalui berbagai asosiasi, organisasi, dan pengelompokan bebas di dalam masyarakat serta keberadaan ruang-ruang publik yang bebas (The Free Public Sphere). Melalui kelompok kelompok mandiri itulah masyarakat dapat memperkuat posisinya face a face negara dan melakukan transaksi-transaksi wacana sesamanya. Sedangkan melalui ruang publik bebas, anggota masyarakat sebagai warga negara yang berdaulat (baik individu maupun kelompok) dapat melakukan kontrol dan pengawasan terhadap negara. Pers dan forum-forum diskusi bebas yang dilakukan oleh para cendekiawan, mahasiswa, pemimpin agama dan sebagainya, ikut berfungsi sebagai pengontrol kiprah negara.
Civil society yang di dalamnya bermuatan nilai-nilai moral tertentu, akan dapat membentengi masyarakat dari gempuran sistem ekonomi pasar. Nilai-nilai itu adalah kebersamaan, kepercayaan, tanggung jawab, toleransi, kesamarataan, kemandirian dan lain sebagainya. Dengan masih kuatnya nilai kepercayaan dan tanggung jawab publik, maka akan dapat dikekang sikap keserakahan individual yang dicoba untuk dikembangkan oleh sistem konomi pasar melalui konsumerisme. Dengan diperkuatnya nilai toleransi dan kesamarataan, maka akan dapat dikontrol kehendak-kehendak eksploitatif yang menjadi salah satu motor penggerak kapitalisme.
Walhasil, civil society baik pada tataran institusional maupun nilai ideal menjadi landasan kuat bagi bangunan demokrasi partisipatoris dan substantif, bukan hanya demokrasi prosedural dan formal belaka. Civil society yang kuat akan mampu mendorong proses politik bukan sebatas ritual atau rutinitas yang hampa makna, karena akan selalu mempertanyakan substansi dari setiap proses. Civil society akan mendorong terciptanya sistem ekonomi yang tidak eksploitatif kendatipun mempergunakan mekanisme pasar. Sistem ekonomi yang peka terhadap distribusi bukan hanya pertumbuhan, kesejahteraan umum bukan kesejahteraan perseorangan. atau kelompok tertentu, kelestarian bukan kehancuran ekosistem, dan tanggap terhadap pengembangan si lemah ketimbang hanya mendukung perkembangan si kuat.
Rezim orde baru terbentuk, dikembangkan, dan dipertahankan semenjak 1967 sampai dengan mundurnya Soeharto 21 Mei yang lalu, merupakan rezim yang memiliki ciri ciri yang sama dengan banyak rezim demokratis otoriter di Dunia Ketiga. Di antara ciri-ciri tersebut adalah: keberadaan negara yang sangat dominan dan mempunyai kekuatan penetrasi sangat luas dan hampir segala dimensi kehidupan serta terjadinya de-politisasi dalam skala massif dalam batang tubuh masyarakat.
Sebagai konsekuensinya, pertumbuhan dan perkembangan civil society senantias mengalami kendala baik struktural maupun kultural, sehingga ia tetap lemah. Karena itulah pertumbuhan dan perkembangan sistem politik demokratis senantiasa berada pada bentuk luar atau institusional dan tidak mampu berkembang secara substantif dan partisipatoris. Negara–yang kemudian menjadi satu dengan kekuasaan satu orang menjadi pemegang monopoli, baik pada arus wacana maupun praksis kehidupan politik, ekonomi dan sosial budaya kita. Melalui strategi-strategi korporatisasi, kooptasi dan hegemoni politik depolitisasi dilancarkan dengan sistematis dan efektif. Pengelompokkan politik, ekonomi dan sosial dalam bentuk orsospol dan ormas diatur sedemikian rupa, sehingga sulit untuk melepaskan diri kontrol dan pengawasan negara. Kepemimpinan politik dan sosial dimasukkan dalam kontrol yang sama melalui jaringan kooptasi dan jika menolak, akan dihadapkan pada represi baik fisik maupun psikis. Hegemoni mengenai ideologi negara, pembangunan, keamanan nasional dan seterusnya dipergunakan untuk memobilisasi kesepakatan (konsen) dari anggota masyarakat terhadap kebijakan politik, ekonomi dan sosial yang dibuat oleh negara.
Akibat langsung terhadap perkembangan civil society jelas sangat negatif. Dengan kontrol yang sangat kuat terhadap organisasi politik, ekonomi, dan sosial berarti secara institusional civil society di Indonesia telah dihalang-halangi pertumbuhannya dan dikontaminasi batang tubuhnya. Kalaupun civil society hidup, maka keberadaannya mirip sebuah bonsai yang keberadaannya hanya sedap dipandang, tapi tidak merupakan pohon yang asli. Dengan perkataan lain, civil society di Indonesia kehilangan jati diri dan ruhnya sebagai kekuatan yang seharusnya mampu membentengi masyarakat dari intervensi negara. Karena itulah, maka elemen-elemen civil society, seperti kelas menengah, ormas sosial dan politik, kaum cendekiawan, mahasiswa, dsb mengalami berbagai distorsi dan paradoks. Kelas menengah, misalnya, merupakan kelas yang tidak banyak berperan dalam proses sosial dan politik karena ketergantungan mereka kepada negara. Kaum cendekiawan pun terbelah-belah oleh primordialisme dan kepentingan politik sesaat, sehingga mengurangi kemampuan mereka sebagai aktor perubahan. Justru yang terjadi adalah bermunculan organisasi cendekiawan yang sejatinya adalah pembungkus kepentingan politik sektarian.
Tetapi, yang lebih memprihatinkan adalah hancurnya landasan nilai yang semestinya menopang civil society. Di bawah orde baru, sistem dan kultur nilai yang menopang sebuah kehidupan publik yang sehat mengalami kemerosotan besar. Dalam hal ini, kepercayaan dan tanggung jawab publik (public responsibility and trust)–yang merupakan ruh sebuah komunitas politik demokratis–mengalami degradasi disebabkan semakin sempitnya ruang untuk berpartisipasi. Penetrasi negara dalam wilayah-wilayah privat, seperti agama dan keluarga misalnya, sangat berperan besar bagi hilangnya kemandirian dan rasa percaya kepada institusi publik. Tambahan lagi politisasi agama dan kelompok agama ikut menciptakan suasana kekhawatiran dan bahkan ketakutan bagi sementara anggota yang merasa tidak di dalamnya. Tak pelak lagi, kecenderungan alienasi, atomisasi dan apati anggota-anggota masyarakat telah memperlemah daya tahan mereka ketika berhadapan dengan penetrasi negara. Masyarakat di bawah lapis, terutama, cenderung bersikap nrimo dan kalau, toh, berusaha bertahan, mereka lebih mengutamakan keselamatan pribadi, bukan keselamatan bersama.
Dalam kondisi civil society seperti inilah, gerakan reformasi muncul dan didorong oleh krisis ekonomi yang menghancurkan salah satu basis legitimasi orde baru yang paling penting. Mahasiswa sebagai kekuatan politik moral berhasil mendorong terbukanya pintu pertama bagi proses reformasi, yaitu turunnya Soeharto dari kepresidenan. Fase berikutnya, yaitu kontestasi antar kekuatan reformasi dan kekuatan status quo masih sedang berlangsung. Dan disinilah sejatinya masa depan pemberdayaan civil society ikut ditentukan. Jika pihak pertama yang unggul, maka kemungkinan pemberdayaan tersebut semakin terbuka, namun jika pihak kedua yang berhasil maka perkembangan civil society di negeri ini akan menghadapi semakin banyak kendala.
Format Demokrasi dan Pemberdayaan Civil Society
Terlepas dari apa yang akan terjadi pada fase-fase berikutnya dari proses reformasi yang sedang berlangsung, satu hal yang pasti: pemberdayaan civil society adalah sebuah keniscayaan apabila bangsa ini ingin bertahan dan sekaligus menjadi bangsa yang demokratis. Untuk itu, sambil terus mengikuti secara seksama dan memperjuangkan proses reformasi ini, upaya-upaya pemberdayaan tak dapat ditinggalkan.
Strategi pemberdayaan civil society di Indonesia dapat dikembangkan melalui beberapa tahapan. Pertama, pemetaan atau identifikasi permasalahan dasar menyangkut perkembangan civil society, khususnya kelompok-kelompok strategi di dalamnya yang harus mendapat prioritas. Pada tahapan ini, diupayakan penelitian atau kajian yang mendalam baik secara umum maupun khusus terhadap potensi yang ada dalam masyarakat untuk menumbuh kembangkan civil society. Umpamanya, pemetaan terhadap segmen segmen kelas menengah yang dianggap dapat menjadi basis bagi tumbuhnya civil society berikut organisasi di dalamnya. Kajian dan penelitian semacam ini sangat penting, agar kita dapat dengan segera melakukan proses recovery dan penataan kembali setelah munculnya kesempatan karena jatuhnya rezim otoriter di bawah Soeharto.
Tahap kedua, adalah menggerakkan potensi potensi yang telah ditemukan tersebut sesuai dengan bidang atau garapan masing masing. Misalnya, bagaimana menggerakkan komunitas pesantren di wilayah-wilayah pedesaan agar mereka ikut memperkuat basis ekonomi dan sosial lapisan bawah? Dalam tahapan ini, jelas harus terjadi reorientasi dalam model pembangunan, sehingga proses penggerakan sumber daya di lapisan bawah tidak lagi berupa eksploitasi karena pola top down. Justru, dalam tahapan ini, sekaligus diusahakan untuk menghidupkan dan mengaktifkan keswadayaan masyarakat selama ini terbungkam. Pendekatan pendekatan partisipatoris harus dipakai dan dalam hal ini bantuan dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) menjadi sangat krusial. Tentu saja, LSM yang dimaksud di sini bukanlah LSM yang hanya berorientasi kepada program saja, tetapi juga pada pemberdayaan.
Pada tingkat kelas menengah, tahapan kedua ini diarahkan kepada penumbuhan kembali jiwa enterpreneur yang sejati, sehingga akan muncul sebuah kelas menengah yang mandiri dan tangguh. Potensi demikian sudah cukup besar dengan semakin bertambah banyaknya generasi muda yang berpendidikan tinggi dan berpengalaman dalam bisnis yang berlingkup global. Para profesionalis muda ini–menurut hemat saya–akan menjadi tulang punggung utama kelas menengah baru yang memiliki kepedulian besar terhadap kemandirian dan pemberdayaan. Hal ini dibuktikan antara lain oleh munculnya kelompok solidaritas profesional muda yang mendukung gerakan reformasi. Mereka menuntut transparansi dan kemandirian dalam dunia bisnis di samping menunjukkan kepedulian terhadap nasib rakyat jelas di lapisan bawah.
Hal yang sama berlaku bagi organisasi kemasyarakatan yang telah berjasa menjadi saluran aspirasi masyarakat selama ini, seperti organisasi-organisasi sosial keagamaan dan LSM. Pemberdayaan kelompok ini sangat penting. Artinya, karena merekalah yang biasanya berada di garis depan dalam membela nasib kaum tertindas melalui aktivitas-aktivitas mereka. Misalnya, permasalahan sosial seperti kemiskinan, keterbelakangan, dan kebodohan diatasi walaupun tentu tidak secara tuntas. Kelompok inilah yang menyuarakan aspirasi masyarakat tertindas baik secara langsung kepada pemerintah maupun publik secara keseluruhan. Sulit dibayangkan seandainya pihak-pihak seperti gereja, pesantren, LSM, dan sebagainya ini tidak hadir di tengah-tengah masyarakat pada saat proses penindasan atas nama pembangunan ekonomi dan modernisasi berlangsung.
Pihak lain yang penting untuk dilibatkan pada tahapan ini adalah media massa yang berperan sebagai wilayah publik bebas yang menjadi tempat transaksi wacana publik. Media massa yang tidak terkontrol secara ketat dan selalu dalam ancaman pemberangusan oleh negara merupakan instrumen bagi proses pemberdayaan civil society. Sebab, di sana dimungkinkan penyaluran aspirasi dan pembentukan opini mengenai permasalahan yang berkaitan dengan kepentingan-kepentingan publik, di samping sebagai alat kontrol kepada kekuasaan negara. Dengan tumbuhnya media massa yang memiliki kebebasan cukup luas, maka kehidupan publik akan senantiasa mengalami penyegaran dan masyarakat pun memiliki ruang untuk mengutarakan aspirasinya. Tentu saja, media massa juga memerlukan pengawasan dari publik, sehingga ia tidak menjadi alat manipulasi kepentingan si pemilik, baik bagi penyebaran gagasan-gagasan dan informasi tertentu maupun sebagai bagian dari bisnis. Media massa yang tidak terkontrol sama sekali, justru akan memiliki agenda setting yang sangat kuat, sehingga bisa mendistorsi kehidupan publik.
Tahap ketiga dalam upaya pemberdayaan jangka panjang adalah mengupayakan jangka panjang adalah mengupayakan agar seluruh elemen civil society memiliki kapasitas kemandirian yang tinggi, sehingga secara bersama-sama dapat mempertahankan kehidupan demokrasi. Civil society yang seperti ini dapat menjadi sumber input bagi masyarakat politik (political society), seperti orsospol, birokrasi dan sebagainya, dalam pengambilan setiap keputusan publik. Pada saat yang sama, political society juga dapat melakukan rekrutmen politik dari kelompok-kelompok dalam civil society, sehingga kualitas para politisi dan elit politik akan sangat tinggi. Hubungan antara civil society dengan political society dengan demikian, adalah simbiosis mutualistis dan satu sama lain saling memperkuat dan bukan saling menegasikan. Tentu saja diperlukan waktu yang cukup lama untuk menghasilkan semacam ini, karena situasi ini menandakan telah terjadinya keseimbangan antara negara dan masyarakat.
Proses pemberdayaan civil society akan tergantung kesuksesannya; sejauh mana format politik pasca reformasi dibuat. Jika format tersebut hanya mengulangi yang lama, kendati dengan ornamen-ornamen yang berbeda, maka pemberdayaan civil society Juga hanya akan berupa angan angan belaka. Sayangnya, justru prospek inilah yang tampaknya sedang di atas angin. Kemungkinan terjadinya pemulihan dan konsolidasi rezim lama (a Recovery and Consolidation the Ancient Regime) masih cukup besar menyusul menguatnya pemerintah transisi di bawah Habibie dan melemahnya kelompok pro-demokrasi. Yang terakhir ini semakin diperparah oleh kenyataan oleh makin terasingnya mahasiswa–yang notabene adalah ujung tombak proses reformasi–dari kelompok yang menginginkan perubahan. Mahasiswa akhir-akhir ini kelihatan harus bekerja sendiri dalam menuntut reformasi total sementara para tokoh pro-demokrasi sibuk dengan mainan baru berupa parpol atau asyik dengan agenda-agenda politik sendiri.
Akibatnya, pemerintah Habibie semakin hari semakin menampilkan diri sebagai agenda setter dari reformasi. Sementara, kaum pro-reformasi tampak hanya menjadi pihak yang mereaksi dan itupun kelihatan sering kedodoran. Hasilnya, berbagai kebijakan yang semestinya berlawanan dengan semangat reformasi, pada akhirnya diberlakukan seperti kita lihat dalam kasus UU Kebebasan Berpendapat, dan mungkin UU Politik. Dalam kasus yang terakhir ini, pihak pro-reformasi kecuali mahasiswa malahan tidak kelihatan hidungnya di DPR dan bersikap pasif. Pihak LSM yang mempunyai kepedulian terhadap reformasi pun, masih sedikit sekali yang mengutarakan pendapatnya mengenai paket UU yang jelas akan menentukan format politik kita nanti.
*Tulisan pernah disampaikan pada Seminar “Pemberdayaan Civil Society dan Demokratisasi” yang diselenggarakan oleh Forum Salatiga, tanggal 28 Oktober 1997
Penulis Ulang: Ahmad Ramzy