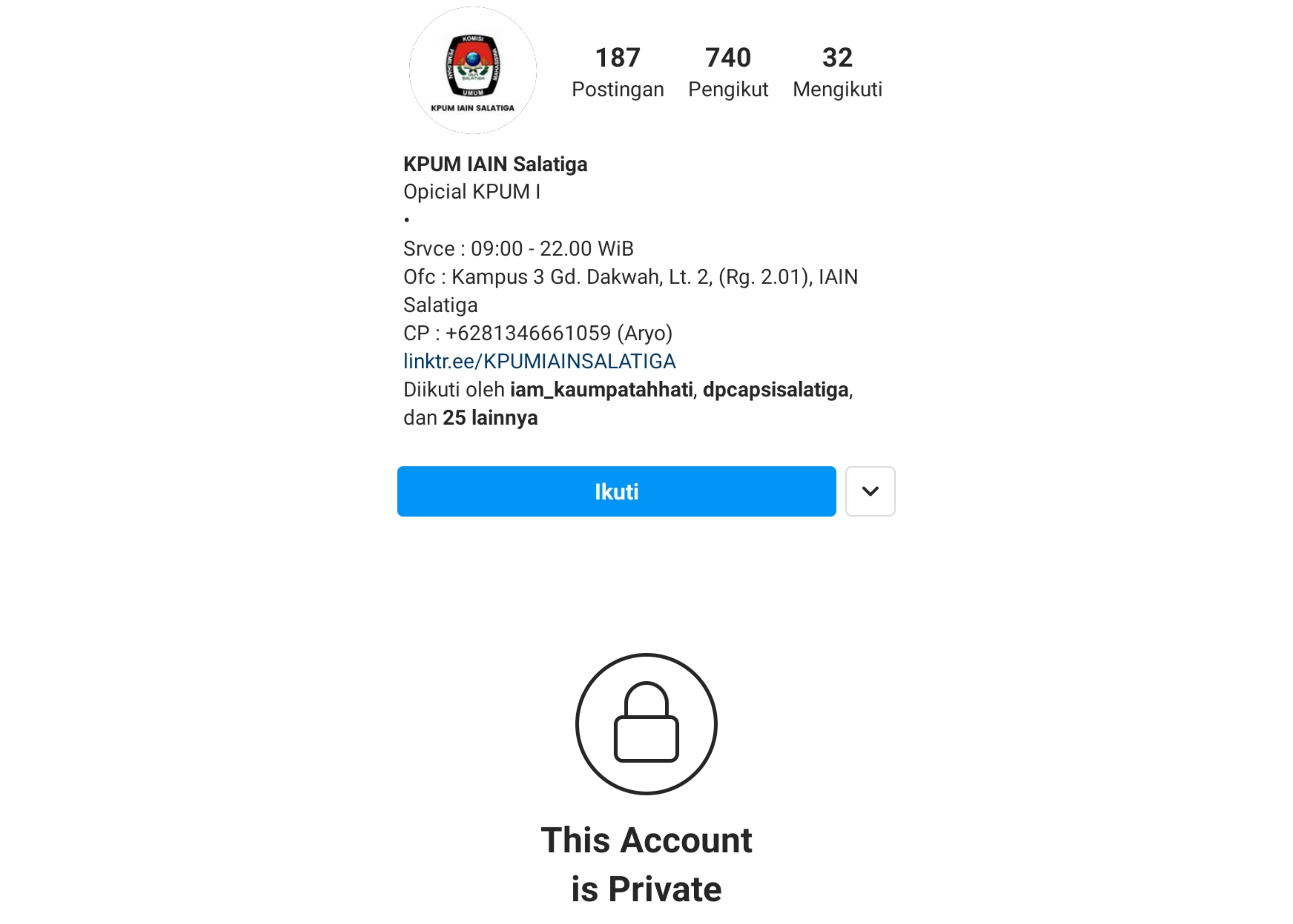Alex tengah menyepi dalam peribadatan Umat Aliran Kepercayaan Sapta Darma di Sanggar Candi Busana, Dusun Legowo, Kabupaten Semarang (Sumber Foto: Izlal/DinamikA)
Oleh: Zakya Zulvita Salsabila
Jika panjenengan berkelana dengan teknologi kuda modern dari Alun-Alun Bandungan, Kabupaten Semarang, menuju Desa Duren, maka hanya perlu waktu 5 menit untuk sampai pada sudut barat daya Alun-Alun Bandungan tersebut. Bukan sembarang daerah, Desa Duren ternyata menyimpan ragam penghayat kepercayaan yang melingkupi masyarakat sekitarnya.
Saat belajar di kelas–dari jenjang dasar sampai menengah akhir–tentu akan mendapatkan pembelajaran yang mengatakan bahwa; agama yang diakui di Indonesia hanya enam agama. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1965, sebelum keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi nomor 97/PUU-XIV/2016, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Khonghucu. Namun, ketika diberi kesempatan singgah–dan setidaknya menyusuri daerah-daerah di sekitar Bandungan, tentu akan menemukan beberapa kepercayaan yang ‘mungkin’ indra kedua baru pertama kali mendengarnya.
Sapta Darma, Kapribaden, Sastro Jendro Hayuningrat adalah beberapa aliran kepercayaan yang akhirnya mewarnai Desa Duren. Terfokus pada pembahasan Sapta Darma, paham Sapta Darma pertamakali diperkenalkan di Pare, Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Oleh Panutan Sri Gutama–atau yang memiliki nama asli Hardjosopoero–yang saat itu dipercayai menerima Wahyu berupa ibadah ‘Sujud’ dengan lafalan keagungan Tuhan dengan bahasa Jawa pada tahun 1952. Berawal dari Sri Gutama, jabatan agung itu kemudian diestafetkan ke Panutan Agung Sri Pawenang (Sri Suwartini)–seorang mahasiswi Universitas Gadjah Mada (UGM) yang meneliti keberadaan Sapta Darma kala itu. Sehingga, pusat Induk-nya kini beralih di Yogyakarta.

Alex berangkat menuju tempat peribaadatan Sapta Darma (Sumber Foto: Mada/DinamikA)
Aliran ini sering disandingkan dengan Islam-Kejawen. Namun, saat reporter LPM DinamikA berkesempatan datang dan mengenal lebih dekat dengan pemangku kepercayan tersebut, kami merasakan tidak ada atmosfer Islam yang dibalut dalam nuansanya. Mereka murni dengan adat kejawen yang menyertai peribadahan mereka.
Alex, ketua penghayat kepercayaan Sapta Darma di Kabupaten Semarang mengungkapkan, “Sapta darma itu termasuk ajaran kejawen, bukan Islam-Kejawen yang sering disalahartikan bahwa kami menganut tentang perdukunan. Padahal, kami sangatlah anti dengan takhayul. Menurut kami, itu bukanlah hal yang benar jika dilakukan,” katanya saat ditemui di ruang tamu rumahnya, Sabtu (13/05/23).
Sapta Darma Bukan Ajaran Baru
Langit mulai petang saat reporter LPM DinamikA sampai di rumah tembok bertekstur garing yang terletak di Dusun Duren milik Alex. Sudah kedua kalinya kami berbincang dan berada di tempat yang sama dengan obrolan yang lebih santai dari sebelumnya. Mengenakan mantel hitam yang cukup kebesaran di tubuhnya, Alex menjamu segelas teh hangat yang sedikit meredakan rasa dingin dari tubuh kami. Sebab, kala itu dia melihat sudah lebih dari 30 menit kami harus berjibaku dengan guyuran hujan.

Tempat peribadatan umat penganut kepercayaan Sapta Darma (Sumber Foto: Mada/DinamikA)
Peristiwa kudeta G30S-PKI tahun 1965 masih terus menjadi momok mengerikan yang menghantui setiap lautan manusia, menjadi saksi sejarah tragis yang menewaskan banyak masyarakat Indonesia. Banyak sektor yang akhirnya terdampak akibat peristiwa besar tersebut. Begitu pula dengan para penghayat kepercayaan yang bagian dari minoritas, mereka turut serta merasakan diskriminasi di situasi merah tersebut. Alex yang duduk di kursi panjang ruang tamu itu mulai mengeja kisah paitnya dengan perlahan.
“Saat itu, Sapta Darma dan masyarakat sekitar masih memiliki kerukunan dengan warga sekitar. Sampai fitnah dari dalam pemangku dusun dan staf desa yang mengatakan bahwa Sapta Darma bagian dari Partai Komunis Indonesia (PKI). Itu adalah diskriminasi terbesar dalam hidup saya, sehingga anak cucu saya harus tau dengan kejadian itu,” ujarnya dengan sedikit mengenang masa tersusah dalam hidupnya, Rabu (2/12/23).
Laki-laki yang memiliki nama asli Adi Pratikto itu melanjutkan kisahnya dengan sedikit menahan sesuatu di matanya. Sesekali, pandangannya ia arahkan ke atas untuk meminimalisir sesuatu yang bening tumpah dari matanya.
“Saat itu, bapak saya dan warga Sapta Darma sedang mengadakan kegiatan di sanggar (baca: tempat peribatan). Tiba-tiba, pemangku dusun datang dengan membawa aparat keamanan. Akhirnya, bapak dan beberapa warga Sapta Darma digeledah dan diamankan. Peristiwa itulah yang akhirnya menyebabkan orang-orang (baca: warga Sapta Darma) itu pada ketakutan. Jadi, ada yang masuk Islam, Kristen, dan hanya beberapa yang tetap pada keyakinannya,” imbuhnya.
Untuk sekarang, di Desa Duren, Dusun Legowo, Bandungan, Kabupaten Semarang, ada sekitar 21 orang yang menganut aliran Sapta Darma dari keseluruhan warga. “Memang masih sedikit sejak kejadian itu, dan orang-orang menganggap itu hal baru. Padahal, Sapta Darma sudah ada lama sekali, tapi baru diresmikan negara sejak 2017,” ujar pria jangkung itu yang meneruskan pembicaraan mengenai perkembangan Sapta Darma yang tersebar di Demak, Grobogan, Kendal, Semarang, Kabupaten Semarang dan 13 provinsi di Indonesia.
Perbincangan yang larut itu terhenti saat suara kumandang azan magrib dari telepon genggam yang dibawa salah satu reporter LPM DinamikA berkumandang keras, semua mata tertuju padanya. Alex yang sadar akan hal itu hanya tersenyum tipis dan menyeruput teh yang ada di hadapannya.
“Silakan teman-teman yang mau sholat monggo, kalian bisa jalan naik ke atas. Nanti, di ujung jalan ada musala. Biasanya di musala ada mukenanya juga,” ucapnya lalu bangkit dari duduknya.
Kepercayaan itu Datangnya dari Hati
Dalam UU No.1 tahun 65 yang telah dibahas di awal tadi, menjelaskan bagaimana negara mengatur kebijakan beragama dan legitimasi terhadap 6 agama yang telah disebutkan. Jika mengamati setiap pemberkasan yang bersifat formal di Indonesia, tentu penyebutan identitas yang di dalamnya termasuk agama tidak dapat lepas dari isi lampiran.
Sebelum putusan Mahkamah Konstitusi nomor 97/PUU-XIV/2016, para penghayat kepercayaan belum dianggap setara dengan agama. Sehingga, setelah keputusan ini dikeluarkan, para penghayat kepercayaan akhirnya dapat bernafas lega dalam menunjukkan jati dirinya.
“Waktu di sekolah itu ‘kan ada mata pembelajaran agama. Itu, kan, disuruh milih, saya milih agama Islam. Tapi, setelah selesai sekolah, ya, saya tetap Sapta Darma. Soalnya, udah nggak ada yang mengikat lagi. Dalam mencari pekerjaan pun sama, kami kesulitan soal identitas. Jadi kalo mau daftar Pegawai Negri Sipil (PNS) kesusahan,” kenang Pak Alex.

Berawal dari Sri Gutama, jabatan agung itu kemudian diestafetkan ke Panutan Agung Sri Pawenang (Sri Suwartini)–seorang mahasiswi Universitas Gadjah Mada (UGM) yang meneliti keberadaan Sapta Darma kala itu (Sumber Foto: Mada/DinamikA)
Obrolan itu terjadi di sela-sela perjalanan kami menuju sanggar dengan berjalan kaki. Tempatnya yang berada lebih tinggi dari rumah Alex, membuat kami sedikit tertatih dan merasakan pegal di sekujur paha dan bagian lutut. Terhitung butuh 5 menit untuk kami sampai di tempat itu.
“Sudah sejak tahun 2006 kami mengajukan permohonan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, karena dalam identitas resmi penghayat kepercayaan ditandai tanda setrip (-) yang diartikan bentuk pemangku penghayat kepercayaan belum diakui setara dengan agama,” lanjut Alex di tengah menyusuri jalanan yang sedikit curam nan licin akibat sisa hujan sore tadi.
“Pengajuan kami akhirnya dikabulan MK tahun 2016 dan proses sampai 2017. Jadi, KTP saya sebelum tahun 2017, di bagian agama itu setrip (-). Tapi, kalau sekarang itu udah ada gantinya, yaitu agama diganti kepercayaan titik dua (:) kepercayaan kepada Tuhan yang Maha Esa,” tambahnya.
Dalam gelapnya malam dan mendungnya suasana Dusun Legowo, Alex yang mengenakan baju batik dibalut mantel itu masih terus menceritakan kehidupannya. Sebentar, ia tersenyum tipis lalu melanjutkan ucapannya dengan tetap berjalan kaki.
“Sejatinya Tuhan itu satu. Tidak ada yang perlu diperdebatkan dengan pemahaman itu. Agama itu buatan negara, karena semestinya kepercayaan itu datangnya dari hati. Jadi, hanya Tuhan dan orang itu saja yang tahu. Harusnya, negara tidak ikut campur masalah beginian. Tapi, ini sudah masa lalu, kalau dibahas terusan malah tidak ada habisnya. Yang jelas kini kami dapat hidup dengan berdampingan,” pungkasnya mengakhiri obrolan panjang itu di depan teras sanggar dan mensilakan reporter LPM DinamikA untuk mengambil gambar di sekitar sanggar tersebut.