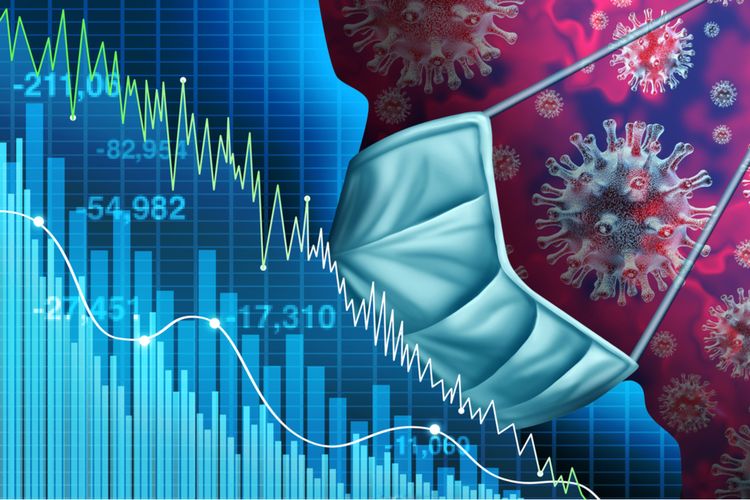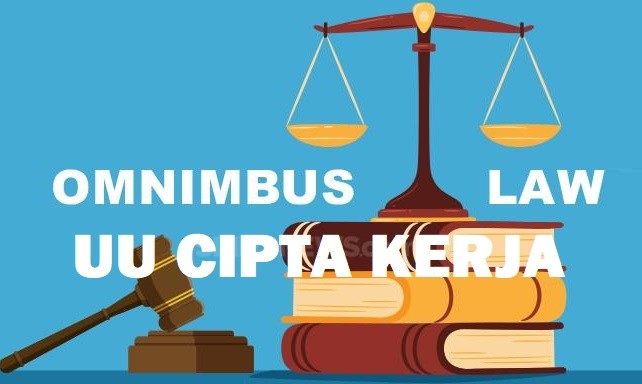Sumber Foto: Kompasiana.com
Oleh: Alfri Mauzizah
Di era kolonial, Kartini menggunakan pena dan kertas untuk menulis surat-surat yang menggetarkan dunia. Kini, di zaman digital, perempuan Indonesia memegang gadget dan keyboard sebagai senjata baru—tapi apakah kita benar-benar mewarisi semangat literasinya?.
Sebagai mahasiswa pemerhati literasi digital, melihat ironi besar: perempuan punya akses lebih luas ke informasi, tapi justru lebih rentan terjerat misinformasi. Jika Kartini hidup hari ini, mungkin ia akan berkata: “Jangan hanya bisa scroll, tapi belajarlah mengendalikan informasi!”.
Dari Surat Kartini hingga Status WhatsApp
Kartini adalah contoh nyata kekuatan literasi sebagai alat emansipasi. Meski terkungkung tradisi, ia menguasai bahasa Belanda, membaca buku-buku Eropa, dan menulis pemikiran kritis. Setiap pucuk suratnya adalah hasil proses literasi yang matang: membaca referensi Belanda, merenungkan kondisi sosial, lalu menuangkannya dalam analisis kritis. Kartini tidak sekadar menulis surat, ia membangun jaringan pertukaran pengetahuan lintas benua. Bayangkan jika ia hidup hari ini: mungkin blog-nya akan dikutip internasional, atau thread-nya viral membahas kesetaraan pendidikan—sebuah pencapaian yang setara dengan mahasiswa S1 masa kini.
Sayangnya, melek huruf belum tentu melek literasi. Survei Programme for intenasional student Assesment (PISA) 2022 menunjukkan 70 persen remaja Indonesia bisa membaca, tapi hanya 30 persen yang mampu membedakan fakta dan opini di internet. Akses informasi yang mudah juga tidak serta-merta menciptakan Kartini-Kartini baru. WHO melaporkan 68% hoaks kesehatan di Indonesia menyasar perempuan, terutama melalui WhatsApp dan TikTok. Ironisnya, di saat yang sama, Perpusnas mencatat hanya 1 dari 10 ibu rumah tangga yang aktif menggunakan layanan perpustakaan digital. Ini menunjukkan kesenjangan antara kemudahan akses dan kedalaman literasi. Ini masalah serius, karena perempuan adalah kelompok paling rentan jadi korban hoaks—mulai dari mitos kesehatan hingga penipuan finansial.
Ini adalah panggilan kami sebagai arsitek informasi untuk membangun jembatan antara data mentah dan pengetahuan yang bermanfaat, memastikan setiap informasi yang tersebar telah melalui proses penyaringan yang tepat. Di laboratorium katalogisasi kampus, kami belajar teknik metadata untuk melacak asal-usul informasi—seperti detektif yang mengikuti jejak digital. Pelatihan knowledge management mengajarkan kami membangun “perpustakaan personal” ala Kartini versi digital: mengklasifikasikan bookmark, membuat catatan referensi, hingga teknik penyimpanan cloud yang terstruktur.
Menulis di Era Digital: Konten atau Kacau?
Kartini menulis untuk mendidik, tapi banyak konten perempuan hari ini justru terjebak tren tanpa substansi. Misalnya saja konten tentang tutorial skincare yang tidak berdasar medis, quote motivasi palsu “kata Kartini”, dan bahkan sampai berita viral yang belum diverifikasi.
Ambil kasus #BijakBersamaTikTok 2023: survei menemukan 7 dari 10 konten “perawatan wajah ala Kartini” justru mengandung misinformasi bahan kimia. Padahal, Kartini sendiri sangat ketat dalam referensi—suratnya kepada Stella Zeehandelaar tahun 1899 bahkan menyertakan catatan kaki dari buku kedokteran Belanda.
Selama magang di lembaga pers mahasiswa, saya belajar bahwa menulis yang bertanggung jawab harus berdasar data seperti Kartini yang merujuk buku, mempertimbangkan dampak seperti surat Kartini selalu punya tujuan jelas, bebas dari bias karena hoaks sering menarget emosi perempuan.
Perempuan Pengelola Informasi
Jika dulu Kartini adalah pustakawan pribadi bagi dirinya sendiri dengan koleksi ratusan buku, kini mahasiswa lulusan program studi yang menyelami dunia literasi informasi bisa menjadi pustakawan digital yang mengajarkan literasi informasi, data analyst yang memastikan data gender tidak bias, ataupun sebagai content creator edukatif yang memerangi hoaks.
Contoh nyata: program “Ibu Melek Data” di perpustakaan daerah, mengajarkan ibu-ibu membaca grafik stunting—langsung berdampak pada kesadaran gizi anak, mereka diajarkan membaca DOI (Digital Object Identifier) pada artikel kesehatan, melacak versi terkini panduan resmi pemerintah, dan membuat content warning untuk info sensitif.
Menurut IFLA Global Vision Report 2023, 82% pustakawan perempuan di Asia Tenggara kini merangkap sebagai : Digital literacy trainer, Community research assistant, dan Local heritage curator.
“Jika dulu Kartini berkata ‘Habis Gelap Terbitlah Terang’, maka versi kita adalah: ‘Habis Hoaks Terbitlah Fakta’!”
Kartini tidak pernah memegang smartphone, tapi semangatnya tetap relevan “Perempuan harus cerdas, bukan hanya bisa like dan share.”
Mari teruskan perjuangannya dengan kritis terhadap informasi, menulis konten yang memberdayakan, dan menyuarakan pentingnya literasi digital. “Dulu Kartini menulis di atas kertas, sekarang kita menulis di atas timeline.”