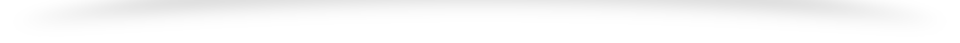Oleh: Lilis Setyowati
“Jod!, jangan jadi mandor! Kerja kerja kerja! Ngalamun bae!” ucap bapak dengan melotot. Aku berlari menujunya. Mengemasi buku gambar dan sebuah pena didalam tasku. Bukan, bukan tas, tapi kantung plastik yang setiap hari kubawa. Perkenalkan, namaku Jod. Aku anak beruntung yang bisa hidup dengan laki-laki tua, yang pernah berencana akan membuangku. Perkenalkan juga, beliau bapakku. Meski begitu, bapak adalah manusia baik, dan aku amat menyayanginya, lebih dari apapun, dari segala-galanya.
Semenjak ibu meninggal, hidup kami berdua jadi lebih tragis, dan mengenaskan. Sering tidak makan, tidak tidur, dan amburadul. Sebagai anak tunggal, aku merasa diberatkan dengan keadaan ini. Keadaan dimana anak berumur sepuluh tahun harusnya pergi belajar, mengerjakan tugas sekolah, bermain layang-layang, dan memakai seragam. Saban hari memikul karung goni, memakai baju kumal, sendal jepit yang seringkali lepas dari pengaitnya, serta berkeliaran di pasar, dan perkotaan, bukan di perpustakaan.
Dahulu, aku tidak pernah berfikir tentang sebuah impian. Darimana asalnya, dimana letaknya, dan apa perannya. Tapi, semenjak bapak sakit, aku jadi memikirkan satu hal besar dalam hidupku. Bahwa impian bukan satu-satunya hal besar. Aku ingin meminta sedikit pada Tuhan. Semoga bapak panjang umur, dan menjadi orang yang konsisten.
Hampir setiap hari, kami berdua pergi ke kota. Menelusuri jalan tikus, dan lorong-lorongnya. Bapak sangat hebat. Beliau bisa jadi apa saya yang diinginkan. Pemulung, tukang sapu jalanan, semir sepatu berjalan, buruh cuci, dan buruh tukang. Bapak tetap hebat, meski pekerjaannya hanya mentok sampai di situ saja.
Mengambil kotak, dan seperangkat alat penyemir sepatu. Menelusuri perkotaan, dan mencari client (bahasa bapak untuk memanggil pelanggan). Setelahnya, kami berdua pergi ke pasar. Mengambil karung goni, dan menuju perkotaan. Profesi utama kami saat ini jadi penyemir sepatu, dan pemulung. Lumayan, untuk membeli makanan pokok.
Di suatu pagi yang cerah, dengan matahari yang lebih kuning daripada telur dadar masakan kami pagi itu, aku dan bapak tengah bergegas untuk berangkat kerja, seperti biasa.
“Jod, kenapa lama sekali anda ini?” ujar bapak.
“Sebentar Pak. Baru menyisir rambut supaya lebih rapi” jawabku.
“Pak, minyak wanginya dimana?, aku minta sedikit saja…” tambahku.
“Halah. Ribet kamu ini, Jod!. Kenapa tidak sekalian pakai dasi?” ucap bapak dengan menegurku di kamar.
“Bolehlah, Pak. Memang bapak punya?” ucapku dengan polos.
“Haduhhh. Dengar Nak, kita ini mau mulung, bersihin sepatu. Kenapa rapi dan wangi seperti ini. Ah, kamu ini!” ucap bapak dengan nada tinggi.
“Bapak, saya jelaskan Pak. Bekerja itu harus rapi, wangi, dan terlihat segar. Jadi, sebisa mungkin….” ucapku.
“Ahh sudah-sudah. Kalau aku mendengarkan nasehatmu, kita tidak jadi kerja hari ini. Ayo, cepat ambil karungnya!. Sudah siang ini!” ucap bapak dengan memotong perkataanku, dan memasang muka masam.
Kami berjalan menuju gang-gang kecil, perkotaan, dan pusat pasar. Berbagai aktifitas masyarakat sudah mulai terlihat. Anak-anak berlarian mengejar angkot, beberapa juga menaiki sepeda beramai-ramai menuju sekolah. Sedangkan aku dengan pomade tebal, rapi, dan wangi tengah membawa karung, berjalan bersama bapak.
Semakin lama, panas matahari memeras kami. Rambutku kembali acak-acakan, wewangianku hilang dengan bau badan yang kecut. Tapi, tak disangka, hari ini pemasukan boleh dikatakan sangat lumayan. Siangnya, kami beristirahat, menuju masjid, lalu menuju restoran minimalis yang kami sebut angkringan. Disana terdapat cakar ayam, sate usus, tahu, beraneka macam gorengan, nasi kucing, dan masih banyak lagi.
Kling ….
Ponsel bapak berbunyi. Ia mengambilnya dari saku, dan buru-buru mengusap layar.
“Jod, kliennnnnya bapak bilang minta sepatunya disemir besok. Di halte, seperti biasa ya!” ucap bapak dengan membaca pesan tersebut.
“Aduh Jod, sepertinya ponsel bapak harus ganti ini!, lihat ponselmu?” tambahnya.
Aku mengeluarkannya dari plastik. Tidak lama kemudian, bapak mengambilnya, dan melihat dari sisi ke sisi.
“Pak, kenapa sih ponsel kita harus bagus. Kita ini kere Pak, buat makan saja susah” ucapku dengan memakan sate usus.
“Jod, sekarang ini, rumah dan makan nomor dua. Informasi nomor satu. Biarlah kita kelantungan, yang penting tidak kudet. Pegang prinsip ini baik-baik” ucap bapak. Aku hanya diam, dan nyengir melihat tingkah bapak.
Satu hari, aku menemukan pagi yang tidak biasa. Kini, bukan lagi untuk jadi pemulung, tapi untuk bertemu dengan seseorang, katanya. Bapak mengajakku berlari. Sesekali mempercepat langkah kaki. Timbul banyak pertanyaan di kepalaku. Tapi, satupun tak berani kutanyakan. Dipegangnya tanganku, dan terpontang-panting tubuhku, hanya untuk bertemu orang misterius, di sudut kota.
“Pak … jangan cepat-cepat. Kakiku rasanya ingin lepas” ucapku dengan gemetar.
“Ah kamu ini, jangan banyak mengeluh, sudah besar kok manja. Saya buang kau, haa?. Diam saja. Paham!”, ucap bapak dengan mimik wajah menakutkan.
Aku terdiam. Tidak ada satu katapun yang ingin aku lontarkan, meski rasanya tidak mungkin apabila bapak benar-benar membuangku. Kalau memang seperti itu, bapak bakal jadi duda miskin yang hidup sendiri. Akhirnya, tanganku dilepasnya. Kaki terasa gemetar, sendal jepit mulai layak untuk dibuang. Cukup kaget, mataku mulai mengajak untuk melirik kesana kemari.
Di sudut kota, terdapat orang-orang mengerikan, dan puluhan ekor monyet. Ditarik kesana kemari, ditendang, dipukul, dan masih banyak lagi perlakuan tidak lazim yang dilakukan oleh orang-orang tersebut. Dari kejauhan, aku melihat bapak mengobrol dengan seseorang, dan diakhiri dengan berjabat tangan. Alhasil kami pulang bertiga. Aku, bapak, dan seekor monyet.
Sesampainya di rumah, aku memberanikan diri untuk menanyakan beberapa pertanyaan. Ia mulai sibuk dengan seabrek peralatan si monyet. Mulai dari rumah-rumahannya, aksesoris, makanannya, dan lain-lain.
“Bapak … bapak apakan dia itu?”, tanyaku.
“Bapak talilah lehernya kuat-kuat!”, jawabnya dengan mengaitkan tali pada leher si monyet, lalu mulai menariknya.
“Pak … tapi, apakah tidak kasihan terhadap monyet itu. Bukankah sejak beberapa bulan lalu, pekerjaan ini sudah tidak boleh dijalankan, Pak?”, ucapku.
“Tau apa kamu tentang pekerjaan ini. kenapa harus kasihan. Ini tidak apa-apa. Tidak akan mati. Mulai sekarang kita tinggalkan pekerjaan sebagai tukang pemulung, dan sebagainya itu, ya!. Sebab, menjadi tukang monyet akan jauh lebih nikmat”, ujar bapak.
“Tapi pak, kasihan monyet itu”, ucapku dengan memperhatikan gerak-gerik si monyet.
“Halah, kau diam sajalah. Tidak harus banyak bicara!”, jawabnya.
“Aku tidak mau pak. Tak tega melihat dia digantung. Saya cari kerja lain saja”, jawabku.
“Heh!, siapa yang gantung? siapa?. Kalau kamu tidak mau, yaa biar bapak saja. Kamu cari pekerjaan yang lain. Asal jangan jadi pengemis. Bapak tidak suka. Dosa!”, ucap bapak.
“Lebih dosa menyiksa dia lah Pak …”, ucapku dengan nada rendah.
“Diam anda, kalau banyak bicara, lama-lama anda yang saya gantung!”, ucap bapak dengan mata melotot.
“Bapak ini, selalu tidak konsisten, pantas saja Tuhan marah!”, ucapku, lalu bergegas masuk kamar.
Disisi lain, aku lebih memilih jadi pemulung, penyemir sepatu, dan semacamnya, ketimbang harus ikut bapak. Selain itu, si monyet selalu dimanja. Makanannya saja, lebih utama dibandingkan aku. Pisang, pepaya, nasi putih yang cerah, selalu habis dimakannya. Sementara aku, dihidangkan nasi kucing, yang kadang memang sudah basi. Heran, rupanya anak bapak sudah beralih jadi monyet nakal itu.
Suatu ketika, monyet gendut itu mengacau. Padahal kami berdua sudah sering melatihnya. Gizinya pun lebih baik daripada anaknya sendiri. Kesehatan, dan kenyamannya selalu diprioritaskan. Siang itu, bapak menyuruhku memberinya makan. Aku hanya menelan ludah, ketika memberinya beberapa pisang yang kuning, dan segar. Naas, aku terkejut ketika tiba-tiba ia menerobos kandang, mengamuk, dan mencakarku beberapa kali. Aku berteriak, memanggil-mangggil bapak.
“Aaaaaaa!. Tolong Pak, tolong!. Dia menggigit telingaku!. Dasar monyet!”, ucapku dengan berteriak, dan menangis.
Tiba-tiba bapak muncul. Spontan, ia yang sedang membawa cangkul, langsung saja memenggal kepala monyet nakal itu. Aku terdiam, dan menangis memegangi telingaku yang hampir saja lepas. Bapak buru-buru mengambil kepala monyet itu, menciumnya, dan melemparnya dalam lubang, lalu menguburnya.
Beberapa jam, aku berada di ruang operasi, pada salah satu rumah sakit setempat. Telingaku dijahit, karena gigitan si monyet nakal. Tangan, dan wajahku terdapat banyak sekali luka. Bapak memandangiku. Aku melihat kedua matanya berbinar-binar. Seusainya keluar dari ruang operasi, beberapa suster tengah mengecek infusku. Tidak lama kemudian aku tidur.
Pukul 03.00 WIB pagi. Aku terbangun, merenggangkan badanku sedikit, dan mendapati bapak tertangkap basah sedang memandangiku. Melihat dari kantung matanya, kukira bapak tidak tidur. Yang aku tahu, tadi siang, ia tengah berupaya kembali bekerja sebagai penyemir sepatu, pemulung, dan profesi multitalenta lainnya. Tapi ternyata, beberapa pekerjaan yang biasa kami lakoni, kini sudah diambil alih oleh orang, akibat ketidakkonsistenan bapak. Tidak bersyukur, dan selalu tergiur oleh pekerjaan lain.
“Kondisi bapak terlihat buruk sekali”, ucapku. Tiba-tiba bapak pergi begitu saja.
“Pak, mau kemana?”, tanyaku.
“Pergi ke masjid. Mengadakan sebuah perundingan. Ini tidak bisa dibiarkan. Hidup kita mulai kacau lagi. Aku akan mengambil air wudhu, dan mulai bernegosiasi. Pukul 03.00 WIB, Tuhan sedang diujung langit”, ucapnya.